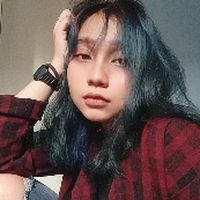Pelecehan seksual kerap menjadi isu sosial yang belum menemui titik terang penyelesaian, terutama di Indonesia. Tak hanya lemah payung hukum, di ranah masyarakat pun pelecehan seksual bukan dianggap suatu urgensi yang perlu disadari dan diatasi. Tak ayal para korban-dari gender perempuan maupun laki-laki-tak pernah benar-benar mendapatkan keadilan, sehingga memilih untuk menutup mulut karena terbentur nilai dan norma yang ada.
Lemahnya perlindungan para korban bisa dibuktikan dari kasus pelecehan seksual yang dialami Pradikta Wicaksono atau akrab yang disapa Dikta baru-baru ini. Mantan vokalis Yovie & Nuno itu menjadi korban pelecehan seksual setelah manggung di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Usai Dikta turun panggung, penonton yang sebagian besar perempuan, langsung menyerbunya dan diduga salah satu fans memegang alat vital sampai meraba-raba tubuh Dikta.
Dalam sebuah video yang menunjukkan aksi pelecehan seksual yang dialami Dikta itu, terlihat dirinya menahan sakit di bagian perutnya, sampai harus dibopong beberapa orang untuk membantunya berjalan. Video itu pun langsung memicu beragam komentar masyarakat dunia maya.
Sayangnya, di antara komentar bernada iba dan miris, terselip komentar bernada mengejek hingga menjadikannya lelucon. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran dan kepedulian masyarakat pada korban pelecehan seksual terutama pada laki-laki masih sangat minim.
 Ilustrasi pelecehan seksual pada pria/ Foto: Freepik Ilustrasi pelecehan seksual pada pria/ Foto: Freepik |
Toxic Masculinity yang Melekat
Bergulirnya komentar para netizen tentang kasus pelecehan seksual Dikta memperlihatkan double standard pada gender yang tak terhindarkan. Segelintir masyarakat menganggap bahwa pria yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual seharusnya bisa melawan atau harus mampu melindungi dirinya sendiri.
Wajar bila sebagian besar korban pria memilih untuk bungkam karena menganggap apa yang terjadi pada dirinya adalah aib, seperti yang terjadi kepada para korban kasus kekerasan seksual yang dilakukan Reynhard Sinaga yang sempat menghebohkan publik Inggris beberapa tahun silam. Bungkamnya para korban pria bukan tanpa sebab. Rasa malu dan takut akan pandangan masyarakat menjadi alasan mereka memilih diam daripada harus mengungkap jati diri dan mengakui bahwa mereka adalah korban pelecehan.
Inilah pemikiran yang termasuk dalam toxic masculinity. Toxic masculinity atau maskulinitas beracun sendiri adalah produk dari peran gender tradisional yang menindas dan membatasi peran laki-laki. Dalam pemahamannya, pria diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan standar "maskulinitas" yang tidak manusiawi dan tidak realistis dominan, tangguh, agresif, kuat, tidak emosional, dan lain sebagainya.
Dari kacamata sosiologis, stigma peran gender tradisional yang toksik telah mempersulit pria korban kekerasan seksual untuk mencari bantuan dan mendapatkan keadilan yang layak. Stigma juga memainkan peranan penting dalam mempengaruhi pandangan publik terhadap korban laki-laki.
Nilai-nilai toksik yang telah terlanjur diamini oleh masyarakat kita ini menjadi alasan utama sulitnya menolong korban dan mengetahui jumlah kasus kekerasan serta pelecehan seksual pada pria yang tidak dilaporkan. Menurut Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA), dalam survei yang melibatkan 60 ribu lebih responden mengungkapkan bahwa 1 dari 10 pria pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik.
Semua itu tidak terlepas dari pikiran bahwa mereka yang tak mampu memenuhi citra maskulin sepenuhnya dan menantang peran gender akan lebih terancam secara sosial dalam masyarakat patriarki. Tak heran jika kebanyakan korban dirundung ketakutan dianggap sebagai individu yang kurang maskulin atau gagal mematuhi standar jika melaporkan kasus mereka.
 Ilustrasi pelecehan seksual/ Foto: Freepik Ilustrasi pelecehan seksual/ Foto: Freepik |
Semua Bisa Jadi Korban
Apapun alasannya, pelecehan seksual atau kekerasan seksual adalah tindakan tak bermoral yang dapat mempengaruhi hidup seseorang. Selama ini, banyak orang berpikir bahwa pelecehan maupun kekerasan seksual hanya bisa dialami oleh perempuan, karena perempuan lemah tak bisa membela dirinya. Pada sisi lain, pria kerap dianggap mempunyai fisik dan mental lebih kuat untuk menangani kasus ini.
Padahal, semua orang bisa jadi korban, semua bisa mengalami pelecehan di lingkup keluarga maupun ruang publik. Namun, kentalnya nilai-nilai patriarki yang sulit ditembus menjadi alasan mengapa banyak korban pria enggan untuk melapor bahkan mencari bantuan ketika mengalami kekerasan dan pelecehan seksual.
Adapun beberapa laki-laki yang melaporkan tentang pelecehan yang mereka alami masih merasa sulit. Kebanyakan korban laki-laki menerima tanggapan yang negatif, seperti tidak dipercaya sebagai korban dan kasusnya dianggap sepele. Terlebih payung hukum mengenai kekerasan seksual di Indonesia, belum tersemat kuat sampai ke akar.
Oleh karena itu, satu-satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah pentingnya edukasi dan menyebarkan kesadaran akan korban pelecehan serta kekerasan seksual bukan hanya menimpa perempuan. Sebab, mendukung para korban terlepas apapun gendernya adalah tanggung jawab kita sebagai masyarakat yang bermoral.
Dukungan yang diterima mungkin akan menimbulkan keberanian dari para korban untuk melawan para pelaku yang mungkin masih berkeliaran di luar sana. Suara dan gerakan masyarakat yang semakin peduli juga diharapkan akan semakin memperkuat perlindungan terhadap korban maupun pencegahan kasus serupa agar terulang kembali di masa mendatang.
(DIR/alm)