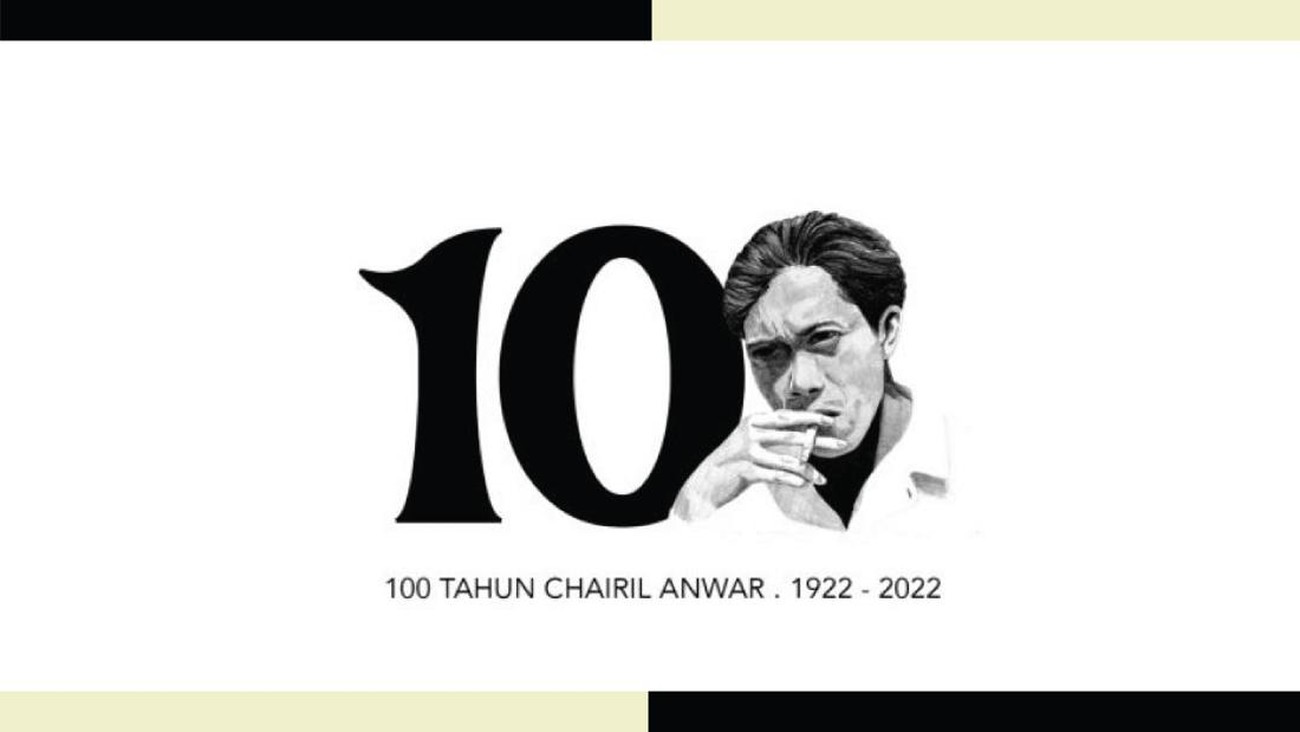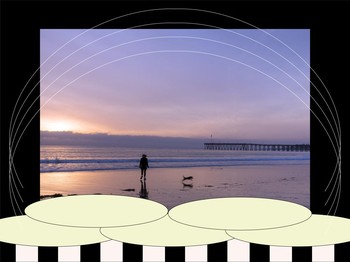Seratus tahun yang lalu, tepatnya 26 Juli 1922, Chairil Anwar dilahirkan di Medan. Tahun yang sama ketika Ki Hajar Dewantara mendirikan Tamansiswa di Yogyakarta. Sebuah perguruan yang pada akhirnya menjadi rumah singgah Chairil di penghujung usia; di mana para pelajar Tamansiswa Garuda, Jakarta, turut mengiringi sang penyair ke rumahnya yang abadi: Karet sebagaimana yang dituliskan di puisinya apa Yang Terampas dan yang Putus.
Sependek 27 tahun hidupnya, Chairil menciptakan 70 puisi, 4 puisi saduran, dan menerjemahkan sekitar 10 puisi lainnya, juga menuliskan 6 prosa, dan 4 kali menerjemahkan prosa lain, yang kebanyakan termuat pada tiga buku yang diterbitkan setelah Chairil meninggal, antara lain Deru Campur Debu (1949), Kerikil Tajam dan Yang Terempas dan yang Putus (1949) dan Tiga Menguak Takdir (1950) bersama Asrul Sani dan Rivai Apin.
Kurang lebih, itulah seintip bibliografi Chairil; sosok yang disebut sebagai penyair Induk di Indonesia, pelopor Angkatan '45, sekaligus pemuda fenomenal nan necis yang berulang kali jatuh dan patah hati kepada perempuan di sekitarnya. Lebih dari itu, banyak yang bercakap-cakap dan membayangkan: Akan jadi apa bahasa dan sastra Indonesia tanpa Chairil dan karyanya? Sebab memang, sejak debut di majalah Panji Pustaka pimpinan HB Jassin, 20 puisi dari Chairil yang kala itu baru berumur 20 tahun, hadir sebagai pembeda, meski tidak seluruh puisinya bisa dimuat karena satu dan lain hal.
Di masa itu sendiri, puisi memang sarat melankolia, perjuangan, dan kekaguman terhadap alam, khas sastrawan pujangga baru yang terkenal romantis dan dominan. Meski demikian, Jassin yang tahu bahwa puisi Chairil sulit diterima redaksi bimbingan Jepang tersebut, justru memperkenalkan karya Chairil kepada sejumlah sosok sentral di kebudayaan Nasional seperti Sjahrir, Kepala Sekolah Tamansiswa Jakarta, dan beberapa tokoh seni lain dengan pesan tersirat, kalau kita punya penyair dan puisi yang mampu jadi pembeda.
Tak ayal jika akhirnya, hari wafatnya Chairil: 28 April, diperingati setiap tahun sebagai hari puisi Nasional. Ini memang tepat. Sebab sampai hari ini, puisi dan kisah hidup Chairil Anwar, sang anak broken home dari zaman kemerdekaan; terus dibaca, dikritik, dipahami, juga dikenang, di seluruh Nusantara atau bahkan dunia. Agaknya, keadaan ini adalah proyeksi yang dimaksud Chairil, "Aku ingin hidup seribu tahun lagi."
Bukan Cuma 'Binatang Jalang'
Chairil adalah sosok yang sangat rakus membaca dan belajar meskipun hanya sekolah sampai SMP waktu itu Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO). Menariknya, beberapa karya Chairil yang saduran atau terjemahan, pernah dianggap sebagai puisinya, walaupun belakangan mulai diketahui Karawang-Bekasi adalah saduran dari The Young Dead Soldier karya Archibald MacLeish, dan beberapa karya lainnya juga disebut menyadur atau sebagai plagiat dari sastrawan dunia terdahulu.
Akan tetapi, kecemerlangan Chairil melalui karya yang lain termasuk Aku yang monumental sulit untuk dipisahkan meski terlampau sering diabaikan. Tidak seperti Aku yang dirawat baik oleh zaman; entah oleh Cinta dan Rangga dalam Ada Apa Dengan Cinta, buku-buku di sekolah, atau telaah puitis pujangga media sosial, puisi-puisi lain Chairil malah ditinggalkan dalam rak-rak buku yang mulai usang.
Di dalam Aku, Chairil memang memuat peluru emasnya, yang jatuh pada "Aku ini binatang jalang/dari kumpulannya terbuang//" Atas dasar itu pula, Chairil kerap disebut sebagai 'Si Binatang Jalang' yang individualis, menggebu, sarat nuansa eksistensialis dan semacamnya, senada dengan kisah hidup atau puisinya yang lain yang juga dituduh 'serampangan' dan tidak kenal aturan. Akan tetapi, Chairil bukan cuma soal 'Binatang Jalang'. Bersama karya-karyanya yang tak kalah dikenal, sebut saja penggalan "Mampus kau dikoyak-koyak sepi" dalam Sia-sia, "sekali berarti sudah itu mati" dalam Diponegoro, atau "Ayo! Bung Karno kasi tangan mari kita bikin janji"' dalam Persetujuan Dengan Bung Karno, agaknya Chairil sendiri membuktikan bahwa isme-isme yang dilekatkan padanya tidak sepenuhnya melekat pada dirinya.
Lagipula, jika dicermati lebih lanjut, Chairil dan angkatan 45, sebagaimana yang disebut Asrul Sani dalam Surat Gelanggang (1951) merupakan ahli waris yang sah dalam kebudayaan dunia, yang mendobrak kesusastraan nasional. Ia adalah penyair yang melahap banyak karya, demi menelaah gaya pujangga baru dan merevisinya menjadi bentuk kekaryaan yang lebih progresif dan relevan. Sebut saja puisi Diponegoro, Perjanjian dengan Bung Karno, atau Karawang Bekasi. Juga kolaborasinya pada poster buatan seniman Affandi yang revolusioner, dengan kalimat "Bung, Ayo Bung" yang membakar semangat sementara konon ceritanya, Chairil mendapati kalimat tersebut pada salah satu bilik prostitusi di Jakarta.
Tentu Chairil memang beda. Bekalnya pun luar biasa. Ia bukan hanya melahap banyak karya penyair dunia di masa itu dan menuangkannya ke dalam karya, namun juga menguasai 4 bahasa: Indonesia-tentu saja, Inggris, Belanda, dan Jerman. Tak heran apabila Chairil kerap dipengaruhi karya Hendrik Marsman, Slauerhoff, Nietzsche, Conrad Aiken, hingga Andre Gide, yang puisinya disalin Chairil menjadi Pulanglah Dia Si Anak Hilang, dan masih banyak lainnya.
Pengayun Pedang Ke Dunia Terang
Hasan Aspahani bilang, layaknya petani, Chairil adalah tukang hibrida puisi. Satu rumus dari seorang pemulia puisi, yang berupaya menyerap, memenggal, menyelipkan hingga membongkar karya para pemuka sastra dunia pada karya-karyanya yang tidak kalah besar.
Pada akhirnya kita sendiri bisa melihat, betapa menggugahnya karya Chairil yang pada saat itu seperti menelanjangi gaya bersastra pujangga baru, meskipun dirinya sendiri tidak luput dari unsur mencari perhatian dan memiliki hasrat untuk turut bergabung ke dalam kelompok yang dominan tersebut.
Bersama Asrul Sani, Rivai Apin, Chairil Anwar disebut Jassin sebagai angkatan 45 jalur pena. Mereka adalah pendobrak dominasi pujangga baru yang lelet. Chairil sendiri hobi menentang bagaimana Takdir, Jassin, dkk. dalam berkata-kata. Secara sompral, Chairil pernah mengungkap kepada Jassin pada suratnya tertanggal 11 Maret 1944 yang kira-kira mengujarkan bahwa Pujangga Baru adalah epigones yang tak tentu tuju. Sebuah kritik yang juga diulang Chairil dalam Hoppla! yang mengejek kalau penyair Pujangga Baru tak memiliki corak kesusastraan.
Chairil memang beda. Ia adalah pemuda berbudaya tinggi dengan jiwa yang larut dan besar di jalanan. Bacaannya jauh menembus budaya eropa yang penuh krama, namun perangainya seperti menggembel tak keruan, walau terus disiplin dalam berkarya. Bahkan dirinya disebut terpaksa berpisah dari Hapsah, Ibu dari buah hatinya, Evawani Alissa, karena kedisiplinannya menjaga ide: bahwa puisinya bukan pendulang uang meski hidupnya kala itu jauh dari kata berkecukupan.
Meski demikian, Chairil Anwar: hidupnya, karyanya dan semua-semuanya memang penuh kesan. Racikan puisinya memuat keluwesan bahasa lisan sehari-hari, yang kala itu semacam mengolok sastra meski akhirnya malah memperluas khasanah kesusastraan nasional yang masih sangat muda. Gamblangnya, Chairil adalah pemroklamir gaya puisi baru yang sampai saat ini terus dipakai dan dipinjam formulanya oleh banyak pujangga pendatang baru.
Joko Pinurbo bahkan menyebut, karya Chairil seperti karya yang baru dibuat kemarin sore. Ia terus relevan dan memberi makna bagi penikmatnya Sementara penyair yang ada di zaman ini, seperti hidup di era lampau yang jauh tertinggal. Lagi-lagi, mungkin inilah penegasan hidup seribu tahun lagi yang chairil nyatakan. Jadi, jika selama ini sosok Chairil sebatas dianggap pemuda pengagum rokok dengan kerah putih yang lurus dan rapi, rasanya itu tidaklah tepat. Sebab Chairil, tidak melulu soal pemuda yang berlagak bebas dan menantang generasi tua, namun Chairil juga seorang ekspresionis dan vitalis, sekaligus prajurit disiplin yang berdiri di garis depan, "yang mengayunkan pedang ke dunia terang".