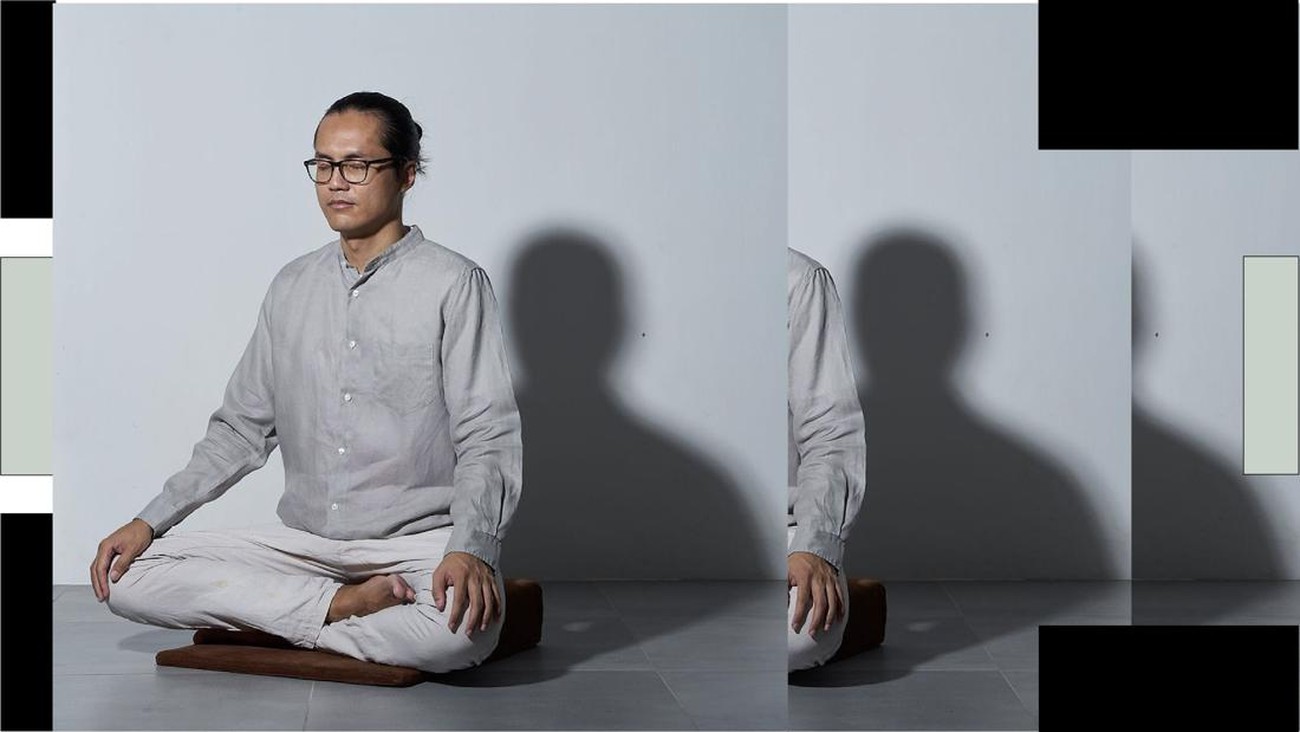Dua dekade yang lalu, isu kesehatan mental mungkin masih tabu untuk dibicarakan. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang lazim untuk dibicarakan, dan mereka yang memiliki permasalahan dengan kondisi mentalnya harus menanggung rasa malu. Beda zaman, beda generasi. Hari ini, meski stigma tersebut belum sepenuhnya menghilang, tapi setidaknya kesehatan mental lebih bisa dibicarakan secara terbuka terutama di kalangan anak muda.
Bagi generasi yang tumbuh besar ditemani media sosial, perbincangan menyangkut kesehatan mental menjadi sesuatu yang familiar dalam keseharian. Bahkan, istilah-istilah seperti healing dan mindfulness menjadi sangat lazim digunakan di media sosial. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu kesehatan mental dan praktek pemulihan batin, CXO Media berbincang dengan Adjie Santosoputro, seorang praktisi kesehatan mental sekaligus pendiri dari Santosha Emotional Healing Center.
Sebagai generasi milenial, nama Adjie Santosoputro cukup dikenal di kalangan anak muda dan siapa pun yang tertarik dengan isu kesehatan mental. Namanya juga semakin dikenal ketika dirinya berkolaborasi dengan Kunto Aji dalam Pilu Membiru Experience. Seperti apa pengalamannya sebagai praktisi kesehatan mental? Simak perbincangan kami dengannya berikut ini!
 Adjie Santosoputro/ Foto: Instagram Adjie Santosoputro/ Foto: Instagram |
Ceritakan sedikit mengenai perjalanan Anda menjadi praktisi kesehatan mental sampai akhirnya mendirikan Santosha Emotional Healing Center.
Setelah saya lulus SMA, saya kuliah psikologi di Universitas Gadjah Mada. Saya memilih jurusan itu karena memang saya sudah memiliki ketertarikan perihal kesehatan mental, terutama kesehatan mental saya sendiri. Saya mulai berminat di kesehatan mental sejak remaja, karena latar belakang keluarga saya memang tidak seperti keluarga pada umumnya, saya lahir di keluarga broken home. Walaupun sebenarnya saya punya minat lain juga di luar psikologi, saya, waktu itu tertarik juga untuk mengambil ilmu komputer, elektronika dan instrumentasi, atau teknik informatika. Tapi akhirnya saya diterima di psikologi.
Lalu setelah lulus kuliah saya lanjut menekuni ilmu psikologi. Cuma dulu saya itu pernah memutuskan untuk jadi pesulap, dan sempat jadi bisnis juga. Tapi entah mengapa di perjalanan saya menjadi pesulap, saya jatuh sakit. Sakitnya saya ini setelah ditelusuri ada kaitannya dengan kesehatan psikis saya yang berkaitan dengan masa kecil saya, karena kemarahan saya, karena dendam, dan kecemasan. Zaman dulu belum ada istilah overthinking, belum ada istilah insecure. Lalu akhirnya saya memilih berhenti jadi pesulap dan memberhentikan bisnis saya juga.
Lalu saya fokus memulihkan diri saya dan saya belajar mengenai mindfulness serta meditasi, dan salah satu cara belajar saya adalah dengan menulis. Dulu masih (ramai menggunakan) Facebook ya, terus ada teman yang suka dengan tulisan saya dan kebetulan dia kerja di penerbitan buku di Solo dan akhirnya menjadikan tulisan-tulisan saya buku. Kalau Santosha memang saya punya niat bahwa kalau saya bergerak sendiri sebatas begitu-begitu saja. Maka setelah saya menekuni bidang tersebut cukup lama, dan bisa dikatakan single fighter gitu, terus saya punya ide gimana kalo dikembangan dengan bikin Santosha akan ada lebih banyak orang yang bisa terbantu.
Selama menjadi praktisi kesehatan mental, apa pengalaman paling berkesan ketika sedang membantu orang-orang, utamanya anak muda, yang ingin memulihkan batinnya?
Di satu sisi, sebenarnya saya pun belajar banyak dari teman-teman yang bercerita ke saya. Sebab saya jadi bisa memahami banyak hal atau banyak sisi dari kehidupan ini. Tapi untuk sekarang ini kalau diminta memilih satu, pernah ada satu momen, kalau dulu belum ramai istilah healing ya. Saya pernah dihubungi anak muda, anak ini menghubungi saya karena dia ingin bertemu dengan saya dan mengobrol dengan saya. Tapi di situ saya juga dihubungi oleh orang tuanya, jadi saya kontak dengan bapaknya, ibunya, dan juga saudaranya. Mereka semua tidak saling mengerti kondisinya satu sama lain.
Saya jadi melihat bahwa hidup ini ternyata banyak sudut pandang. Apa yang kita rasa paling benar, ya ternyata belum tentu juga. Saya juga bersyukur akhirnya mereka bisa saling memahami karena mereka bisa bertukar sudut pandang. Si anak muda merasa "oh orang tuaku begini". Tapi lalu orang tuanya bercerita, mereka bisa seperti itu karena ada masa lalunya yang juga pahit, jadi kompleks sekali. Tapi kalau kita bisa melihat berbagai sudut pandang ternyata lebih bisa menenangkan.
Apakah ini menjadi satu tantangan juga untuk menjadi praktisi kesehatan mental, yaitu untuk bisa mendengarkan dari berbagai sudut?
Ya itu memang resiko di bidang saya karena saya mesti mendengar dengan sepenuh hati, siapapun yang bercerita ke saya. Ada satu jurus atau teknik, yaitu deep listening atau mendengarkan dengan tanpa menghakimi. Ketika sedang mendengarkan biasanya kan pikiran kita langsung terbagi "oh ini pelaku", "oh ini korban". Kita langsung cenderung sepenuhnya memihak korban, tapi ternyata kalau di counseling ya gak bisa sepenuhnya begitu. Bahkan ketika pelaku bercerita ke saya, saya pun perlu meletakkan dulu judgment saya, saya perlu melepaskan dulu prasangka buruk saya atau mungkin asumsi-asumsi saya
Bisa mendengarkan mungkin suatu keterampilan atau kekuatan, tapi di satu sisi itu juga kutukan gitu. Dulu juga ada misalnya kasus perselingkuhan, ada yang cerita ke saya pasangannya selingkuh. Sehingga kan, ya manusiawi saya langsung berpikir 'ni korban dan yang satu adalah pelaku yang selingkuh'. Tapi setelah beberapa waktu, yang sebelumnya saya judge sebagai pelaku juga akhirnya bercerita ke saya. Lalu kan saya gak bisa menghakimi dia, saya menutup telinga dan menyalahkan dia, kan gak bisa begitu. Ya itu yang jadi tantangan dan itulah yang sebenarnya menguras energi saya dan teman-teman saya di bidang seperti ini. Kelihatannya cuma mendengarkan, tapi itu sebenarnya menguras tenaga.
Bagaimana caranya me-recharge energi setelah melaksanakan sesi-sesi itu?
Ada beberapa cara saya, ini buat saya pribadi ya. Beberapa di antaranya adalah saya mesti meluangkan waktu untuk bermain. Bermain bisa bermacam-macam, misalnya beberapa bulan ini saya merawat anjing saya dan dia hampir setiap saat mengajak saya bermain. Mungkin juga misalnya dengan bertemu keponakan saya yang anak kecil, itu juga saya bisa bermain bersama dia. Atau bisa juga dengan musik, berkesenian.
Berkesenian itu juga bisa membantu me-recharge energi, kalau saya biasanya bermain gitar. Dan yang terakhir yang paling esensial adalah saya bermeditasi. Saya grounding, menjangkarkan diri saya di present moment. Itu bisa banyak variasinya juga, misalnya saya berjalan dengan nyeker, bukan nempel di lantai tapi benar-benar menapakkan kaki saya di tanah. Lalu bisa juga mendekatkan diri ke alam, agar kena sinar matahari. Itu sih beberapa teknik saya untuk me-recharge energi.
Kesehatan mental semakin bisa dibicarakan secara terbuka di kalangan anak muda. Menurut Mas Adjie, apa yang masih menjadi tantangan terkait isu kesehatan mental di Indonesia?
Generasi sekarang itu kayak antitesanya dari generasi yang dulu. Generasi sekarang, meski tidak semuanya, cenderung sedikit-sedikit mengaitkan dengan kondisi mental. Generasi sekarang, meski tidak semuanya, mungkin cenderung meromantisasi dan mengglorifikasi persoalan mental. Dengan kecenderungan untuk meromantisasi ini, ada sebagian yang akhirnya addicted to pain. Mereka jadi sulit pulih dari cemasnya, karena dengan meromantisasi cemasnya itu dan dengan terus-terusan ngomong di sosial media bahwa dirinya cemas, dia merasa diperhatikan dan merasa mendapatkan identitas di situ. Itu malah menyulitkan teman-teman kita yang benar-benar mengalami gangguan kecemasan. Itu satu kondisi yang mungkin perlu kita urai, perlu kita atasi bersama-sama.
Kedua adalah edukasi akan kesehatan mental yang masih sangat kurang. Baik yang memberikan edukasi maupun peminatnya, kesadaran untuk mengikuti edukasi mental itu masih sangat kurang. Kalau kita lihat polanya, persoalan kesehatan mental ini kan kalau di sisi penanganannya itu selama ini kita berpikir harus konseling, harus ke psikolog. Ya saya setuju itu kita harus psikolog, harus ke profesional, harus ke psikiater. Tapi kenyataannya, masyarakat Indonesia, anak muda Indonesia, sebenarnya masih terhalang stigma, masih sulit untuk konseling. Sehingga sebelum konseling sebenarnya perlu adanya satu tahap sebelumnya yaitu psikoedukasi, dan di situlah Santosha ada sebenarnya, dengan memposisikan diri sebagai bimbel sehat mental.
Sehingga sebelum konseling, barangkali ada lebih banyak teman-teman yang tergerak hatinya untuk belajar lebih dulu. Karena kalau semuanya langsung ke konseling, jumlah psikolog dan psikiater di Indonesia itu masih sangat kurang. Jadi perbandingannya itu sangat tidak sehat, sehingga nanti psikolog atau psikiater akan sangat kewalahan dalam menangani. Di situlah psikoedukasi itu menjadi penting.
Melihat bagaimana pengalaman Adjie terjun melihat secara langsung kondisi mental masyarakat, khususnya generasi muda dalam menangani kesehatan mental, membuat kita harus membuka mata juga. Di satu sisi, kita perlu membicarakan kesehatan mental secara terbuka demi menghapus stigma-stigma yang ada. Tapi di satu sisi, muncul konsekuensi akan kecenderungan untuk meromantisasi dan mengglorifikasi kesehatan mental.
Sebenarnya, generasi muda hari ini cukup beruntung bisa memiliki sosok yang bisa memandu mereka dalam hal kesehatan mental. Sebab, di era di mana laju informasi tak terbendung, isu kesehatan mental justru bisa melahirkan mitos-mitos baru. Di sinilah pentingnya peran praktisi kesehatan mental untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan mental yang menyeluruh dan tepat.
(ANL/DIR)