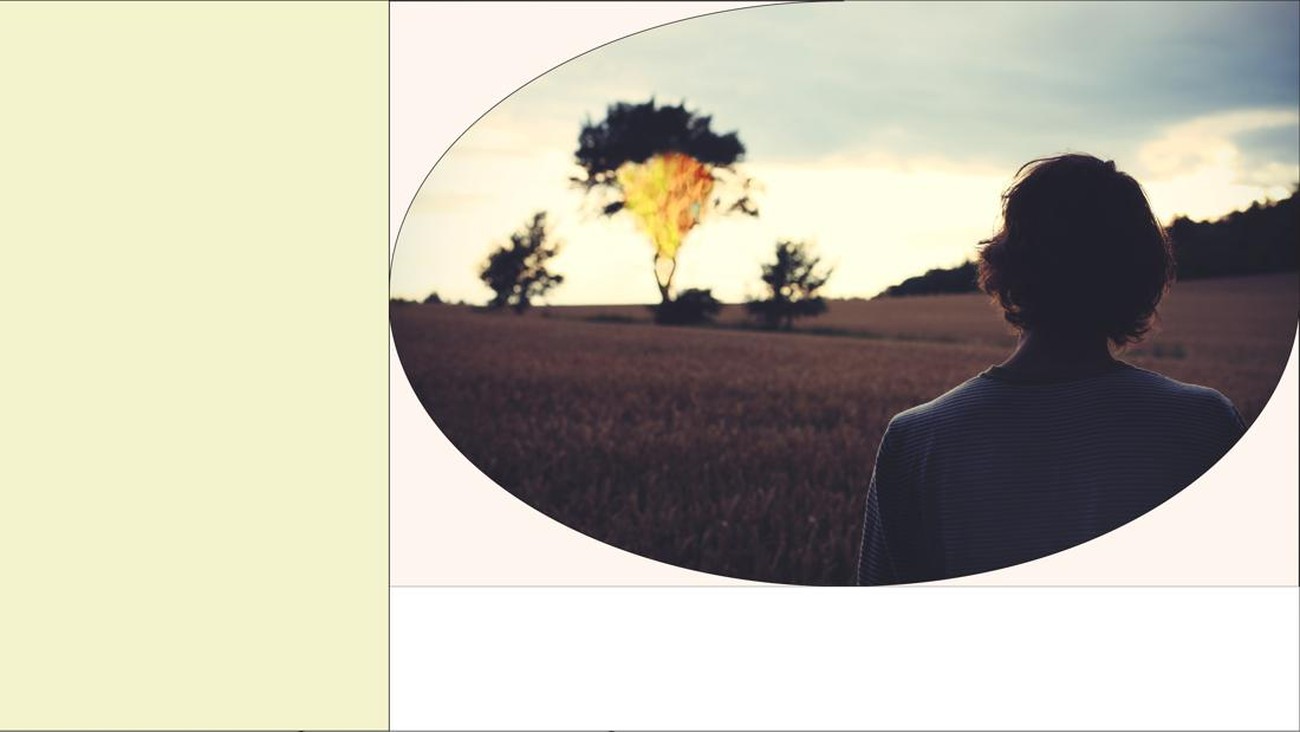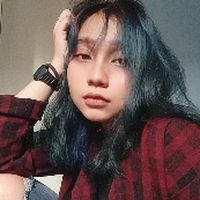Dalam sebuah percakapan sehari-hari, menurut saya ada tiga hal yang paling sungkan saya bicarakan, pandangan pandangan politik, identitas seksual, dan agama yang dianut. Ketiga hal tersebut cukup sensitif dibicarakan dan memiliki kemungkinan besar menjadi konflik, apalagi soal agama. Tinggal di negara berketuhanan dengan enam agama, mungkin membuat sebagian besar hidup kita dipenuhi nilai-nilai agama.
Tak bisa dimungkiri juga, di dalam tiap keluarga Indonesia, setidaknya menganut satu agama dan menjadi suatu warisan dari generasi ke generasi. Meski begitu, di tengah masyarakat yang kental nilai keagamaan, nyatanya masih ada individu-individu yang merasa bimbang dengan agama yang dianutnya. Salah satunya adalah pengalaman pasangan saya yang pernah menjadi seorang agnostik.
Agnostisisme merupakan sebuah bentuk pemikiran penerimaan batas-batas epistemologis pengetahuan manusia dan batas-batas pemahaman manusia yang pada akhirnya kabur. Penganut agnostisisme seperti pasangan saya, Tio, memerlukan pemahaman mendalam akan misteri eksistensial dan hal-hal yang bisa dibuktikan secara empiris terhadap keberadaan Tuhan. Sehingga dalam kurun waktu 4 tahun lamanya, Tio bercerita tentang pencariannya mencari Tuhan dan agama yang menurutnya paling masuk akal.
 Ilustrasi mencari Tuhan/ Foto: Lukas Rychvalsky - Pexels Ilustrasi mencari Tuhan/ Foto: Lukas Rychvalsky - Pexels |
Pencarian Tuhan
Tio berkisah, ia memutuskan untuk menjadi agnostik ketika berumur 20 tahun. Saat itu, dia mempertanyakan semua alasan mengapa kita harus beragama, mengapa kita tidak mencari kebenaran tentang agama yang kita anut selama ini, dan apakah agama itu sebuah warisan atau pilihan. Bukan sesuatu yang mudah dijalani menjadi seorang agnostik di tengah lingkup sosial yang menjunjung tinggi agama. Dan hal tersulit ketika menjalaninya adalah tekanan sosial yang memandangnya sebagai seorang pengecut dan tidak mempercayai Tuhan.
"Yang paling sulit bagi aku adalah pandangan orang tentang agnostik itu merupakan seorang pengecut. Karena mereka menganggap kita tidak bisa mengambil keputusan untuk memilih salah satu agama. Selain itu, aku juga dianggap enggak percaya Tuhan. Padahal agnostik itu berbeda dengan atheis yang enggak percaya Tuhan sama sekali."
"Saat itu aku berpikir bahwa kita tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada dan kita juga tidak bisa membuktikan Tuhan itu tidak ada. Makanya bisa aku berada di tengah-tengah antara kelompok yang beragama dan percaya Tuhan (Theist) dan yang tidak beragama serta tidak mempercayai eksistensi Tuhan (Atheist)," kata Tio.
Selama menjalani agnostisisme, Tio melakukan semua ritual agama yang dilakui oleh masyarakat. Mulai dari mengerjakan salat ke masjid, menjalani ibadah ke gereja, pergi ke pura, ke vihara, hingga pergi ke klenteng pun ia lakukan. Semua itu hanya demi satu tujuan yaitu, mencari keberadaan Tuhan. Namun bukan perkara mudah, untuk membuat orang lain memahami apa yang sedang dilakukan oleh Tio.
 Ilustrasi agnostik/ Foto: Spencer Selover - Pexels Ilustrasi agnostik/ Foto: Spencer Selover - Pexels |
Seringkali orang-orang yang mengetahui Tio yang seorang agnostik, tidak segan untuk meremehkannya, menjauhinya, dan melabelinya membawa pengaruh buruk karena mereka takut agnostisisme bisa 'menular'. Padahal menurut Tio sejauh ini para agnostik tidak punya keinginan untuk mempengaruhi orang lain agar menjadi agnostik juga. Ia hanya ingin mencari tahu kebenaran tentang eksistensi tertinggi, namun masyarakat kita justru lebih memilih untuk menghakimi orang-orang sepertinya, bukan memberikan fasilitas pengetahuan agama yang mereka butuhkan.
"Kalau aku, setiap ditanya agama, selalu yang aku sebut ya agama warisan orang tuaku, karena kalau aku mengaku sebagai seorang agnostik pasti ada saja hujatan atau sindiran yang tak enak didengar. Dulu saat belajar agama, tiap kali aku tanya tentang keberadaan Tuhan sama orang yang beragama, jawabannya justru 'percaya aja', 'memang begitu ajarannya', atau 'jangan dipertanyakan'. Lalu, kalau ditanya lebih mendalam lagi akhirnya malah emosi. Jadi, enggak ada jawaban yang benar-benar buat aku puas," ucapnya.
Menjadi seorang agnostik juga cukup berat di lingkungan keluarga yang mungkin berpandangan lurus tentang agama. Namun di lingkup keluarga Tio yang menjunjung tinggi pluralisme, ibu Tio yang mengetahui anaknya seorang agnostik tidak serta-merta memarahi atau mengecilkannya. Tapi justru memberikan pandangan-pandangan agama yang dianutnya tanpa memberikan paksaan. Selain itu, teman-teman terdekatnya yang mengetahui Tio yang belum menganut agama apapun, justru membantunya untuk menemukan arah.
Pada perjalanannya, Tio yang masih tak tahu arah agama itu pun terus mencari jawaban keberadaan Tuhan dari berbagai pemuka agama, membaca hampir semua kitab suci untuk mencari kebenarannya, mempelajari mulai dari mitologi yang paling primitif, animisme, dinamisme, politeisme-monoteisme, sejarah ketuhanan, pengaruh budaya dan agama, psikologi agama, moralitas, dan masih banyak lagi.
 Ilustrasi Islam/ Foto: Meruyert Gonullu - Pexels Ilustrasi Islam/ Foto: Meruyert Gonullu - Pexels |
"Selain belajar, aku juga ngobrol-ngobrol sama teman-temanku yang Islam, Hindu, Budha, Katolik, Kristen, Konghucu, atheis sampai yang sesama agnostik untuk berdiskusi tentang keberadaan Tuhan. Tapi aku selektif dalam memilih orang untuk diajak berdiskusi tentang topik sensitif ini," ungkapnya. Namun setelah perjalanan selama 4 tahun untuk memilih agama yang ingin dianut, Tio akhirnya memutuskan untuk menganut Islam. Tapi bukan karena Islam yang paling benar dari semua agama, tapi karena menurutnya agama tersebut adalah agama terlengkap dari yang ia cari selama ini.
"Memilih Islam juga karena menurutku yang paling lengkap saja. Walaupun masih ada beberapa hal yang masih aku pertanyakan sampai sekarang. Apalagi kalau cuma percaya. 'Mempercayai' dan 'Mengetahui' itu dua hal yang berbeda lho. Menurutku memang masih kurang masuk akal. Tapi toh, semua agama memang tidak ada yang 100 persen masuk akal. Aku berharap, masyarakat lebih open-minded dan mencontohkan lewat perilaku jika ingin membuat kita percaya tentang suatu kepercayaan. Bukannya malah mengucilkan atau menghakimi. Hanya itu kekurangan masyarakat kita," tutupnya.
Mendengar kisah pasangan saya yang pernah hidup menjadi seorang agnostik, membuat perspektif saya terhadap keagamaan mulai terbuka. Sebagai sesama manusia yang mempercayai adanya kehidupan di dunia ini, agaknya kita mesti rendah hati untuk memilih tidak menilai baik atau buruk dan mensyurga-nerakakan seseorang hanya dari kepercayaan yang dipilih.
Bukankah sejak kecil kita sering diajarkan untuk bertenggang rasa dan menerima pluralisme yang ada di sekitar kita? Jadi, terlepas apapun yang dipercaya seseorang, sebaiknya kita memang menghormati pilihan masing-masing.
(DIR/MEL)