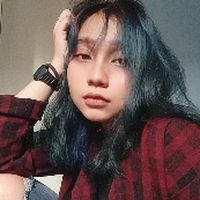Bukan rahasia bahwa perkara kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia tak pernah turun secara signifikan. Walau pun patut diapresiasi bahwa jumlah pengaduan kasus kekerasan pada perempuan tahun 2022 yang tercatat di Badilag mengalami penurunan dari 459.094 kasus di tahun 2021 menjadi 457.895 kasus, jelas bahwa jalan masih panjang bagi penanggulangan kekerasan terhadap perempuan di negara ini.
Jika dilihat lebih lanjut, pengaduan ke Komisi Nasional Perempuan justru meningkat dari 4.322 kasus menjadi 4.371 pengaduan. Artinya, rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus dalam sehari. Kesimpulannya, kasus kekerasan pada perempuan jalan di tempat alias begitu-begitu saja bahkan cenderung meningkat di ranah tertentu, seperti ranah personal.
Komnas Perempuan mencatat ada 422 kasus kekerasan dalam pacaran, 622 kasus kekerasan pada istri, 140 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, 111 kasus kekerasan pada kerabat dekat, 90 kasus kekerasan dari mantan suami, dan yang tertinggi adalah 713 kasus kekerasan dari mantan pacar. Data-data seperti ini menunjukkan betapa sulitnya memberantas kekerasan berbasis gender terutama pada perempuan.
Masih banyak angka yang tidak saya jabarkan dalam artikel ini karena saking banyaknya kasus kekerasan pada perempuan yang tercatat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada 2023. Sementara menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa), laporan kasus pada Januari 2024 saja sudah ada 2.756 kasus kekerasan pada perempuan.
Menurut kelompok umur, yang paling banyak mengalami kekerasan adalah rentang usia 13-17 tahun (30,5%), 25-44 tahun (29,5%), dan 6-12 tahun (15,1%). Ranah yang paling sering menjadi tempat kejadian kekerasan ini adalah dalam lingkup rumah tangga yakni 58,4%. Itu pun yang tercatat, lantas bagaimana kekerasan pada perempuan yang tidak dilaporkan? Misalnya di daerah terpencil yang masih menganut adat-istiadat yang kental dan tak teredukasi dengan baik perihal ini.
Terbentur Stigma
Jujur saja, kasus kekerasan di daerah pelosok dan terpencil seakan tabu untuk dibicarakan dan dicari solusinya dengan alasan jauhnya akses untuk mengedukasi mereka hingga keterbatasan biaya dari komisi-komisi terkait. Karya Jeremias Nyangoen, Women From The Rote Island, akhirnya membuka mata banyak orang bahwa kekerasan pada perempuan di wilayah terpencil Indonesia adalah nyata dan termasuk dalam kategori darurat.
Film ini menggambarkan sebuah realita yang ironis bahwa wilayah terpencil Indonesia yang masih memegang adat-istiadat yang kuat sangat rentan terjadi kekerasan pada perempuan. Pelakunya pun bukan orang lain, melainkan orang terdekat.
Kepada CXO Media, Jeremias mengatakan kisah yang ia angkat dalam film merupakan kisah nyata yang banyak dialami oleh perempuan di daerah terpencil. Karakter Martha hanyalah satu dari sekian banyak perempuan daerah yang tak tertolong karena menjadi korban.
"Saya punya alasan sendiri mengapa saya membuat film ini. Saya punya argumen yang saya dapatkan berdasarkan fakta di lapangan. Dari hasil observasi saya, penduduk negeri ini-rata-rata suku-suku terasing di kampung-kampung masih percaya bahwa kodrat seorang perempuan hanya sebatas menjadi istri, ibu, dan melayani suami saja," ujarnya saat bertandang ke kantor CXO Media beberapa waktu lalu.
Pria yang akrab disapa Jerry itu pun mengatakan kekerasan dalam rumah tangga-terutama kekerasan seksual masih dianggap tabu bila diungkapkan dalam masyarakat. Bahkan ada pemikiran jika melapor justru yang dianggap salah adalah korbannya perempuan maupun anak laki-laki yang mengalami pelecehan seksual. Mereka malu dan takut untuk melapor kepada pihak berwenang. Walhasil, siklus kejahatan ini tidak pernah terputus, sebab pelaku masih melenggang bebas.
"Saudara kita di kampung itu, mereka diperkosa ya hanya menerima pasrah. Menerima saja [karena]mau lapor ke mana? Saya bersyukur bahwa undang-undang itu (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) ada, tetapi praktiknya, aplikasinya, belum tentu sampai ke bawah (masyarakat terpencil) karena Indonesia itu sangat luas, lantas gimana caranya?" kata Jerry.
Minimnya Akses Perlindungan Korban
Sebenarnya pada 2023 lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memandang pentingnya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di wilayah-wilayah terpencil dan pelosok Indonesia. Menurut mereka, seharusnya daerah pelosok menjadi prioritas pemerintah untuk mencegah hingga menanggulangi korban kekerasan-anak dan perempuan.
Sayangnya fakta di lapangan berkata lain, Anggota KPAI, Dian Sasmita mengatakan saat ini belum semua kabupaten/kota mempunyai UPTD PPA, terutama di wilayah-wilayah di Indonesia Timur. Sedangkan, sekarang baru ada 254 UPTD PPA di seluruh Indonesia. Ya, jauh dari kata banyak bahkan cukup.
"Menurut kami ini harus dijadikan prioritas serius pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait bagaimana mengupayakan kebijakan khusus supaya pemda bisa dengan mudah mendirikan atau menyediakan layanan UPTD PPA," kata Dian seperti dikutip Antara.
Dian menambahkan ketiadaan UPTD ini berandil besar kepada korban ketika ingin mengakses layanan pendampingan dan pemulihan ketika proses hukum. Ingin melapor pun korban sulit untuk mendapatkan informasi, apalagi ketika harus berhadapan dengan visum.
Padahal dalam aturan tertulisnya, fungsi pendampingan dan pemulihan harus dijalankan oleh bidang perlindungan anak apabila UPTD PPA belum tersedia di suatu daerah. Tidak adanya layanan ini, membuat tenaga profesional yang seharusnya disediakan untuk membantu korban justru tidak hadir di saat-saat terberat mereka.
"Ini menambah lagi derita pada korban. Tidak ada juga bantuan hukum khusus untuk korban. Ini berlipat-lipat sekali kondisi para korban ini," lanjut Dian.
Meskipun untuk sekarang layanan yang bisa menanggulangi korban masih terbatas, namun sejujurnya perubahan datang dari diri sendiri dan didukung keluarga dan orang-orang sekitar. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani pun meminta korban kekerasan tidak takut untuk melaporkan kasusnya pada pihak berwenang.
Sementara pihak berwenang polisi semestinya memang dibekali pengetahuan dan penanggulangan awal untuk korban kekerasan yang ingin melapor. Sehingga, tidak ada lagi alasan aparat hukum justru melemahkan korban yang sudah bertekad untuk melapor dan meminta keadilan.
"Menurut saya, aparat-aparat hukum semestinya tidak melemahkan korban kekerasan. Sebab yang saya lihat di lapangan tidak sedikit korban yang akhirnya depresi bahkan nekat bunuh diri karena sudah melapor tapi justru tidak mendapat bantuan. Harus dicari rumusan yang berbeda gitu lho. Dengarkan mereka dulu, kemudian polisi bantu lapor ke Komnas Perempuan, soalnya mereka kan juga tidak paham kalau mengalami ini harus lapor ke mana," ujar Jerry.
Indonesia sepertinya masih punya pekerjaan rumah (PR) yang berat untuk menurunkan angka kekerasan terutama pada perempuan. Informasi dan pengetahuan sepertinya belum cukup untuk bisa menekan angka yang tiap tahun hanya berkutat pada angka yang itu-itu saja. Perlu adanya kepedulian yang lahir dalam diri bahwa setiap orang perempuan, laki-laki, anak-anak, gender apa pun pantas untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan yang setara.
(DIR/tim)