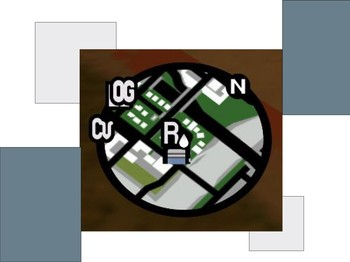Baru-baru ini, selebriti Keke Palmer menjadi perbincangan di Twitter karena dibanding-bandingkan dengan Zendaya. Perbandingan ini terjadi karena seorang pengguna mengatakan bahwa dengan melihat perbedaan dan persamaan antara Keke Palmer dan Zendaya, kita bisa melihat bagaimana colorism bekerja di industri hiburan Hollywood. Konteks dari tweet ini adalah sebagai respons terhadap bagaimana orang-orang baru menyadari prestasi Keke Palmer sekarang setelah ia membintangi film Nope padahal ia sudah memiliki segudang prestasi sejak menjadi artis cilik.
Keke Palmer sendiri tidak ingin dibandingkan dengan siapapun. Ia merespon perbandingan tersebut dengan mengatakan "A great example of colorism is to believe I can be compared to anyone. I'm the youngest talk show host ever. The first Black woman to star in her own show on Nickelodeon, and the youngest and first Black Cinderella on broadway. I'm an incomparable talent. Baby, THIS, is Keke Palmer."
Kalian mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya colorism dengan karir Keke Palmer maupun Zendaya. Keduanya sama-sama merupakan selebriti keturunan Afrika-Amerika, lantas mengapa perbedaan warna kulit mereka bisa memicu perdebatan mengenai colorism? Ini dia segala hal yang harus kamu ketahui mengenai colorism!
Berbeda dengan Rasisme, Tapi Sama Berbahayanya
Secara sederhana, colorism adalah diskriminasi berdasarkan warna kulit. Istilah colorism pertama kali digunakan oleh Alice Walker dalam bukunya yang berjudul In Search of Our Mothers' Gardens (1983). Ia mendefinisikan colorism sebagai prasangka dan diskriminasi terhadap orang dari kelompok ras yang sama berdasarkan warna kulit mereka. Alice Walker sendiri merupakan seorang penulis perempuan keturunan Afrika-Amerika, dan ia merasa dalam komunitasnya ada preferensi terhadap kulit yang berwarna lebih terang.
Berdasarkan apa yang ditulis Walker, dapat disimpulkan bahwa colorism adalah bentuk diskriminasi yang lebih nuanced dibandingkan dengan rasisme. Apabila rasisme merupakan diskriminasi terhadap kelompok ras tertentu, diskriminasi berdasarkan colorism bisa terjadi kepada orang yang datang dari kelompok ras yang sama. Pada dasarnya, semakin terang warna kulitmu-terlepas dari apapun rasmu-kamu akan semakin mudah mendapatkan privilese.
Privilese yang dimiliki oleh orang-orang dengan warna kulit lebih terang telah dibuktikan melalui berbagai penelitian. Salah satunya, penelitian yang dilakukan oleh Lance Hannon, Robert DeFina, dan Sarah Bruch (2013) menemukan bahwa murid perempuan berkulit hitam dengan skin tone yang lebih gelap tiga kali lipat lebih rentan menerima hukuman dibandingkan murid berkulit hitam yang skin tone-nya lebih terang. Selain itu, jurnalis Shankar Vedantam juga menulis dalam bukunya bahwa orang Amerika Latin berkulit terang menghasilkan rata-rata $5000 lebih banyak dibandingkan orang Amerika Latin berkulit gelap.
Colorism Terjadi di Semua Kelompok Ras, Termasuk Asia
Masyarakat Asia sendiri tidak lolos dari colorism. Hal ini terbukti ketika warna kulit yang lebih terang dianggap sebagai standar kecantikan bagi masyarakat Asia, termasuk Indonesia. Di Asia, warna kulit bisa menjadi penanda kelas sosial. Warna kulit gelap identik dengan pekerjaan kasar di luar ruangan, sehingga diasosiasikan dengan kelas pekerja. Sedangkan kulit yang lebih terang diasosiasikan dengan gaya hidup kosmopolitan yang lebih nyaman dan lebih sering berada di dalam ruangan.
Peneliti Ayu Saraswati menggunakan istilah cosmopolitan whiteness untuk menggambarkan fenomena standar kecantikan di Indonesia. Menurutnya, cosmopolitan whiteness adalah gagasan kulit putih yang tidak mengacu pada ras tertentu. Dengan bantuan beragam produk kecantikan, siapapun bisa membuat kulitnya menjadi lebih terang. Buktinya, krim pemutih masih menjadi produk kecantikan yang paling diminati.
Keinginan untuk memiliki kulit yang lebih putih sendiri sudah ada sejak masa kolonialisme, terutama saat Jepang menduduki Indonesia. Melalui iklan produk-produk kecantikan Jepang, kulit putih digambarkan sebagai standar ideal. Sehingga bagi masyarakat Asia Tenggara, kecantikan ala Asia Timur dengan kulit yang putih pun menjadi acuan. Sampai sekarang pun hal ini masih terjadi, salah satunya dibuktikan dengan banyaknya artis Korea Selatan yang menjadi bintang iklan untuk produk kecantikan yang dipasarkan di Indonesia.
Meski colorism bisa tumpang tindih dengan rasisme, tapi harus diakui bahwa keduanya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa ras dan warna kulit adalah isu yang kompleks. Colorism memiliki konsekuensi yang sama berbahayanya dengan rasisme, karena ia mewajarkan diskriminasi. Colorism memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan inequality bagi orang-orang berkulit gelap. Oleh karena itu, sudah saatnya kita berhenti berpikir bahwa putih berarti selalu lebih baik.