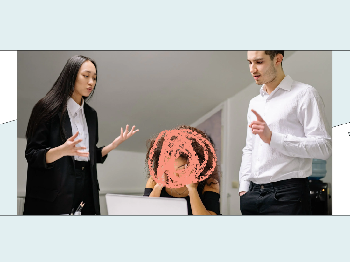Setiap kali kasus perselingkuhan menjadi perbincangan, istilah "pelakor" alias "perebut lelaki orang" pasti menjadi kata kunci yang tak pernah absen dari komentar publik. Istilah ini kembali ramai setelah kasus perselingkuhan yang melibatkan Arawinda Kirana menjadi topik hangat di kalangan warganet. Pemeran film Yuni tersebut diduga memiliki affair dengan seorang laki-laki yang sudah memiliki istri dan anak.
Dalam sekejap, Arawinda langsung menjadi sasaran dari amarah warganet. Ia menjadi target dari body shaming, cancel culture, bahkan laman profilnya di Wikipedia ditambah dengan keterangan "pelakor". Tak hanya sampai di situ, warganet juga menyerbu profil Instagram University of Southern California-tempat Arawinda menempuh pendidikan-dengan memberi komentar "#cancelledarawinda".
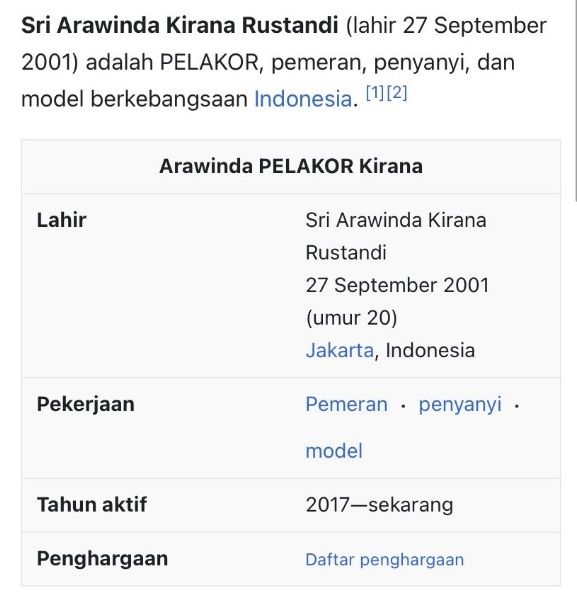 Arawinda Wikipedia/ Foto: Wikipedia Arawinda Wikipedia/ Foto: Wikipedia |
Arawinda selama ini dikenal sebagai salah satu figur publik yang vokal terhadap isu perempuan. Bahkan, Arawinda juga digadang-gadang sebagai sosok Kartini modern. Akibatnya, banyak pihak merasa bahwa citra Arawinda sebagai pejuang hak perempuan adalah omong kosong belaka karena ia "merebut" suami perempuan lain. Tentu saja, bagaimanapun juga perselingkuhan tidak bisa dibenarkan. Namun masalahnya, "pelakor" sendiri adalah istilah yang tak adil secara gender.
Permasalahan pada istilah "pelakor" terletak pada stigma terhadap perempuan, yaitu perempuan dicap sebagai penggoda dan penghancur hubungan suami istri. Menurut Nelly Martin-Anatias, akademisi di bidang sosiolinguistik, kata "pelakor" merupakan retorika yang timpang dan seksis karena berpihak pada laki-laki. Istilah pelakor dikhususkan untuk perempuan. Sedangkan kita sendiri tak memiliki istilah khusus bagi laki-laki yang berselingkuh dan mengkhianati pasangannya.
 Ilustrasi pelakor/ Foto: Pexels Ilustrasi pelakor/ Foto: Pexels |
Istilah "pelakor" menciptakan konsekuensi sosial yang timpang dan berat sebelah. Ketika kita menggunakan istilah "pelakor", kita sedang menyudutkan perempuan sebagai satu-satunya pihak yang bersalah dan pantas untuk dihakimi. Sementara itu, pihak laki-laki bisa lolos dari sanksi sosial dan tak harus menghadapi penghakiman publik.
Selain itu, istilah "pelakor" sendiri juga berpotensi mengobjektifikasi laki-laki. Sebab dengan menggunakan kata pelakor, laki-laki dianggap sebagai objek yang diperebutkan dan tak berdaya atau tak mampu mengambil keputusannya sendiri. Padahal, dalam kasus perselingkuhan pastinya ada dua pihak yang terlibat. Laki-laki turut memiliki peran sebagai kolaborator dalam perselingkuhan yang terjadi. Sebenarnya, sah-sah saja apabila warganet ingin menunjukkan kepedulian terhadap kasus perselingkuhan. Tapi, tak adil apabila publik mengecam sosok perempuan dengan kata "pelakor". Sebab kata "pelakor" sendiri sangat bertolak belakang dengan semangat women support women.
(ANL/DIR)