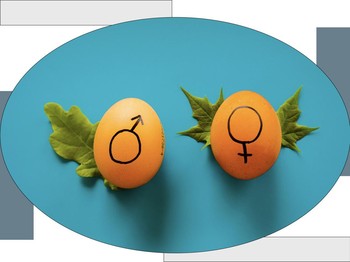Kalau kalian aktif di media sosial, pasti kalian pernah menemukan istilah hyungers. Hyungers adalah sebutan berkonotasi negatif bagi orang-orang yang kerap menambahkan kata 'hyung' di akhir kalimat. Melalui meme yang viral ini, kita bisa melihat bahwa hyungers distereotipkan sebagai mbak-mbak K-popers berhijab yang gemar mengkonsumsi kopi susu dan seblak. Stereotip ini menggambarkan adanya keterkaitan antara gender (dalam kasus ini perempuan) dengan jenis makanan tertentu. Padahal, bukankah laki-laki juga mengkonsumsi kopi susu dan seblak? Lantas, mengapa ada stereotip gender dalam makanan?
Stereotip gender memang hadir di hampir semua keseharian hidup kita. Mulai dari cara berpakaian, selera musik, bahkan hingga makanan. Ada banyak stereotip yang beredar mengenai gender dan makanan. Misalnya, teh lebih identik dengan perempuan sedangkan kopi hitam lebih identik dengan laki-laki. Atau ada juga yang menyebutkan bahwa perempuan lebih gemar mengonsumsi makanan pedas dibandingkan laki-laki. Namun, adakah kebenaran di balik stereotip ini? Benarkah makanan memiliki "jenis kelamin"?
Dikutip dari Scroll, sejarah stereotip gender dalam makanan muncul di tahun 1870an di Amerika Serikat. Pada era tersebut, banyak perempuan yang tadinya perannya sebatas ibu rumah tangga akhirnya mulai bekerja. Meski perempuan bisa beraktivitas di ruang publik, tapi mereka tetap diharapkan untuk berkumpul di ruang-ruang yang dikhususkan untuk perempuan. Akibatnya, saat itu banyak bermunculan bar dan tempat makan khusus perempuan.
Sejak saat itu, banyak media yang membingkai jenis-jenis makanan berdasarkan gender. Berbagai koran dan majalah menerbitkan rekomendasi cemilan, jenis minuman, hingga hidangan penutup untuk perempuan maupun laki-laki. Tak hanya itu, banyak juga strategi marketing produk-produk makanan yang menyasar kelompok demografi gender tertentu.
Memasuki abad ke-20, akhirnya tercipta asumsi bahwa perempuan mengonsumsi makanan yang lebih "halus"--makanan yang bertekstur lembut, makanan yang sehat, hingga makanan yang berwarna-warni. Sedangkan, laki-laki lebih identik dengan makanan yang dicap maskulin, seperti daging dan makanan protein hewani lainnya.
Menurut Silvia Benso, Profesor Filsafat dan Direktur Women's and Gender Studies di Rochester Institute of Technology, makanan adalah budaya dan segala sesuatunya termasuk gender dipengaruhi oleh budaya. Ia menunjukkan salah satu contoh dari relasi antara budaya makan dengan gender adalah adanya tuntutan bagi perempuan untuk selalu terlihat cantik dan langsing. Akibatnya, perempuan diharapkan untuk selalu menjaga tubuhnya dengan porsi makan yang kecil dan jenis makanan yang terbatas pada sayur-sayuran.
Makanan tak seharusnya memiliki jenis kelamin. Sekilas, mungkin stereotip gender dalam makanan ini tidak terlihat berbahaya atau memiliki dampak signifikan. Tetapi, ia bisa digunakan sebagai alat untuk menormalisasi perilaku yang seksis dan diskriminatif. Lihat saja meme hyungers yang beredar di media sosial. Mungkin, meme tersebut bisa membuat kita tertawa. Tetapi meme tersebut pada akhirnya digunakan untuk menyebarkan stereotip negatif mengenai individu-individu tertentu. Lagipula, hal sesimpel dan se-esensial makanan tak seharusnya dibuat rumit dengan stereotip-stereotip tak berdasar.