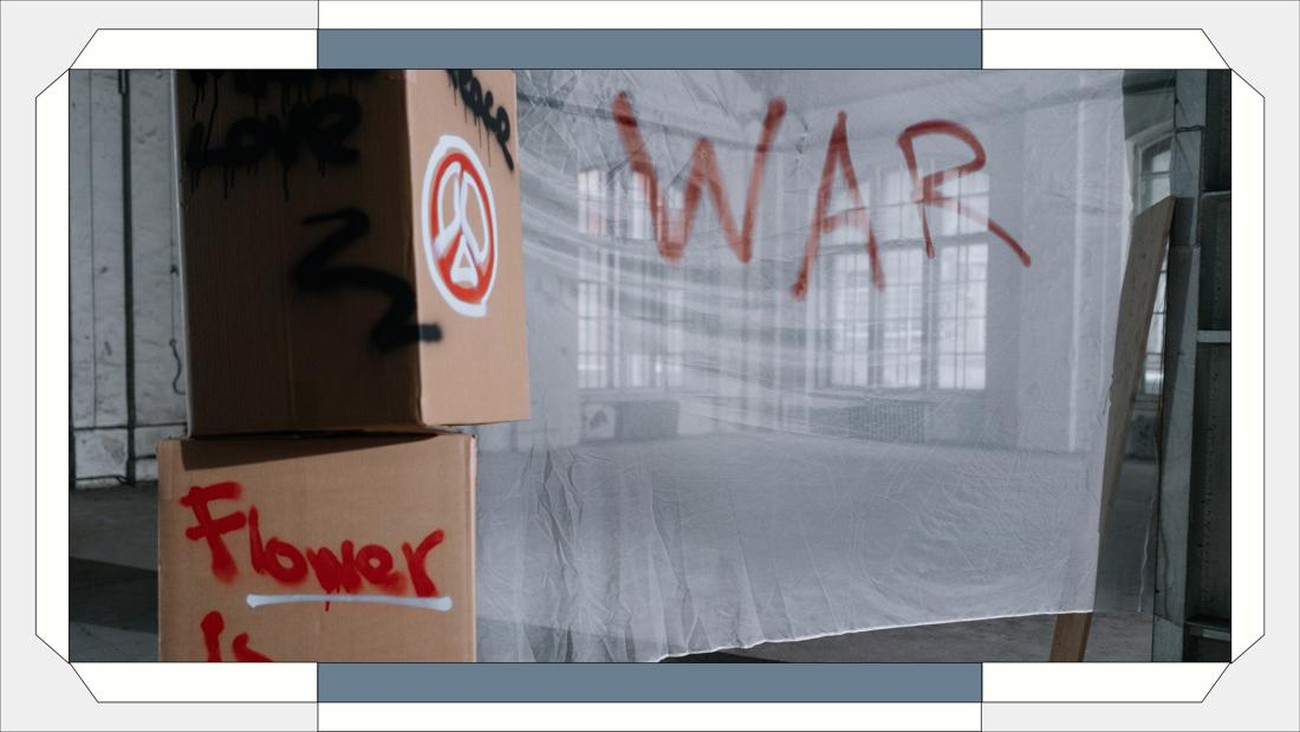"Potong-potong roti, roti oles mentega. Belanda sudah pergi, Indonesia merdeka." Senandung barusan, adalah sisa kegembiraan dari masa kecil saya; yang kembali menyeruak di kepala ketika mendengar permintaan maaf resmi Pemerintah Belanda kepada Indonesia pada pertengahan Februari lalu. Maksudnya, bukankah ini cukup mengherankan? Setelah hampir 77 tahun Indonesia merdeka, mengapa Belanda yang konon pernah menjajah selama 350 tahun, baru menyampaikan maafnya yang mendalam? Kalau memang seperti itu, atas dasar apa permintaan maaf itu ditujukan?
Ternyata, permintaan maaf Belanda tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri, Mark Rutte sebagai respons lanjutan dari temuan penelitian bertajuk "Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945-1950," yang menunjukkan Belanda terbukti melakukan sejumlah kekerasan ekstrem dan sistematis selama masa perang kemerdekaan Indonesia.
Sementara di media sosial, terbukanya kisah kelam ini ditanggapi secara pro dan kontra, khususnya oleh masyarakat dari kedua belah negara--yang memang sempat punya hubungan jangka panjang di masa silam. Contoh utamanya adalah Tweet dari Politisi sayap kanan Belanda Geert Wilders dari Partai Politik Forum voor Democratie (FvD) asal Negeri Kincir Angin yang terkenal populis.
 Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte/ Foto: Mark Rutte/detik.com Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte/ Foto: Mark Rutte/detik.com |
Entah janjian atau memang satu pemikiran, mereka berdua menentang permintaan maaf Pemerintah Belanda. Keduanya bahkan senada mencuitkan, kalau yang dilakukan Belanda dahulu tidaklah salah, dan Indonesia yang seharusnya meminta maaf karena berlaku tidak kalah keras pada periode, yang disebut sebagian orang Belanda dengan istilah 'Bersiap'. Kecaman dari politisi-politisi Belanda tersebut, sontak mendapat serangan balik sporadis dari warganet Indonesia yang terkenal cukup agresif.
Tidak butuh waktu lama, ratusan protes dan sanggahan dilancarkan warganet ke laman Twitter para politisi Belanda tersebut. Saya sendiri, yang kebetulan sedang mempelajari dan mengamati asal-usul sekaligus dampak permintaan maaf Belanda merasa terhibur dengan pro-kontra yang ada. Walaupun Twitwar yang berlangsung sedikit bernada sentimentil, setidaknya kedua kubu tersebut mencoba menyampaikan argumen berdasarkan data masing-masing dan disertai sikap kritis terhadap hasil penelitian dan pengetahuan sejarah.
Sampai di sini, menurut sempit pemikiran saya, agaknya paparan sejarah masa silam yang dihasilkan penelitian tersebut cukup kapabel dalam membuka ruang berpikir dan diskusi publik secara lebih meluas. Bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menjadi referensi bagi penelitian-penelitian serupa berikutnya, secara lebih lengkap dan berimbang.
 Ilustrasi tentara Belanda di era kolonial/ Foto: Thecreatorsproject Ilustrasi tentara Belanda di era kolonial/ Foto: Thecreatorsproject |
Memahami Peristiwa Perang Kemerdekaan 1945-1949
Penelitian bertajuk 'Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan, dan Perang di Indonesia, 1945-1950' ini diinisiasi langsung oleh Pemerintah Belanda pada tahun 2017 lalu. Tujuannya untuk membongkar awan kelabu sejarah leluhur mereka, dan demi kepentingan pembelajaran di masa depan. Dana penelitian sebesar 4,1 juta Euro dialirkan kepada tiga lembaga asal Belanda yakni Institut Kerajaan Belanda untuk Kajian Asia Tenggara dan Karibia (KITLV); Institut Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH); Institut Belanda untuk Studi Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD); juga dibantu tim peneliti asal Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai mitra penelitian regional yang bergerak secara independen.
Kemudian, penelitian ini juga didasari oleh serangkaian fakta-fakta dan penceritaan sejarah, yang sedikit demi sedikit mengindikasikan adanya perlakuan semena-mena militer Belanda pada perang yang disebut Indonesia sebagai periode Revolusi Nasional. Rangkaian kejadian berikut, pada akhirnya semakin menguatkan dugaan kekerasan oleh militer Belanda di Indonesia.
Pemantik paling awal tersampaikan oleh veteran perang Hindia Belanda, Johan Engelbert Heuting. Di tahun 1969, melalui sebuah siaran televisi Heuting mengungkap jika dirinya terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan, khususnya saat bertugas di Jawa Timur (1947) dan Yogyakarta (1948). Pada kurun tersebut, Heuting mengaku menyaksikan sejumlah kekerasan dan pengeksekusian sepihak terhadap orang-orang Indonesia yang tertangkap. Pernyataan ini disampaikan karena berkelindan dengan program doktoralnya, yakni mengapa Belanda enggan menyelidiki kejahatan perang pada masa aksi polisionil di Hindia Belanda.
 Ilustrasi Tentara Belanda berinteraksi dengan warga lokal/ Foto: Wikimedia Commons Ilustrasi Tentara Belanda berinteraksi dengan warga lokal/ Foto: Wikimedia Commons |
Pernyataan kontroversial Heuting itu, lantas meninggikan tensi politis di Belanda. Sejumlah pihak pun sigap membantahnya dengan keras, termasuk para veteran perang. Bahkan dalam menanggapi kesaksian Heuting, pemerintah Belanda sampai menerbitkan Excessennota, atau catatan berlebih atau keterlaluan, yang menarasikan sikap defensif pemerintah yaitu 'memang betul ada yang berlebihan namun Militer secara keseluruhan berperilaku benar'. Jika dimaknai lebih lanjut, ungkapan tersebut merupakan upaya penghalusan bahasa dari pemerintah Belanda demi menghindari istilah kejahatan perang.
Bertahun-tahun setelahnya, narasi tersebut terus dilanggengkan oleh Belanda. Meskipun tidak mulus karena terdapat banyak gugatan melalui karya-karya populer seperti sastra dan juga film-film dokumenter, narasi tersebut tetap bertahan. Sampai pada akhirnya, narasi tersebut harus goyah, karena gugatan Jeffry M. Pondaag selaku ketua Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) bersama pengacaranya, Liesbeth Zegveld, diterima dan dikabulkan pengadilan Belanda di tahun 2011.
Pada tuntutannya, KUKB menuntut pemerintah Belanda untuk membayar ganti rugi pada korban-korban Pembantaian Rawagede, Jawa Barat (1947). Diterimanya gugatan KUKB tersebut, kemudian berefek pada terkuaknya sejumlah insiden lain pada kurun 1945 sampai 1949, tidak terkecuali insiden mengerikan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Konon, dalang utamanya bernama Raymond Westerling. Ja, dat klopt, Westerling. Seorang Belanda yang disebut Om Iwan Fals pada lagu 'Pesawat Tempur' sebagai sosok yang juga bisa tersenyum, adalah otak dibalik pembunuhan sekitar puluhan ribu nyawa di berbagai wilayah Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, yang meskipun terbilang kontroversial, gagal untuk diadili secara sepadan.
Selanjutnya, pemicu paling baru yang semakin memantapkan rencana penelitian di atas muncul ke permukaan pada tahun 2016. Adalah sebuah buku berjudul De brandende kampongs van Generaal Spoor atau Pembakaran Kampung oleh Jenderal Spoor, karya sejarawan blasteran Belanda-Belgia bernama Remy Limpach. Buku itu mengulas kekerasan sang Panglima Militer Belanda Simon Spoor, yang membakar perkampungan orang Indonesia, serta memberi jalan pada kekerasan ekstrem dan meluas di banyak daerah.
 Ilustrasi Agresi Militer Belanda II/ Foto: Wikimedia Commons Ilustrasi Agresi Militer Belanda II/ Foto: Wikimedia Commons |
Dampak Permintaan Maaf dan Penelitian yang Dilakukan Belanda
Penelitian yang dilakukan Belanda untuk membedah persoalan masa lalu yang kelam, memang telah memaparkan bukti sejarah yang cukup faktual pada sejarah Bangsa Indonesia, khususnya pada periode perang revolusi. Sepintas, itikad baik Belanda ini memang layak diapresiasi. Sebab pada hasil penelitian, kekerasan dan kejahatan perang yang selama ini ditutupi Belanda akhirnya dibuktikan benar adanya.
Selanjutnya, keberimbangan porsi dalam penelitian sejarah ini masih terkesan subjektif, menyertakan ego serta kepentingan pihak Belanda. Faktanya, para peneliti asal Indonesia beserta tenaga ahli yang memang benar memahami masalah ini, justru kurang terlibatkan. Lalu, periode penelitian hanya sebatas rentang tahun 1946 - 1949, terbilang cukup kontroversial, mengingat pada masa ini, terdapat tudingan kurang kuat--Belanda mengenai kejahatan Indonesia kepada mereka, yang disebut dengan istilah 'Bersiap'.
Padahal, jika kita mencoba mencermatinya lebih jauh, perang Revolusi Indonesia sebenarnya terjadi karena hasrat ambisius Belanda dan sekutu, yang ingin sekali lagi mengkolonisasi Indonesia, yang sejatinya telah merdeka sejak 1945. Maka tindakan kekerasan yang berlebihan, selayaknya datang dari penyerang, yaitu Belanda, yang mana memiliki niat untuk kembali menjajah Bangsa yang sudah merdeka. Kemudian, rentang waktu penelitian yang hanya berfokus pada pasca kemerdekaan, terlebih khusus pada aksi kekerasan yang sejumlah buktinya telah pudar oleh zaman atau dipudarkan, menjadikan dana 4,1 juta Euro atau setara Rp 66,7 miliar seperti sia-sia dan tidak optimal.
Jika benar niat penelitian ini untuk mengungkap sejarah kelam antara kedua negara ini benar ingin dilakukan Belanda, maka menyentuh tragedi sepanjang masa kolonial Belanda di Indonesia wajib dilakukan. Sebab pada kenyataannya, sikap kejam Belanda sebagai penjajah lebih banyak ditemui di masa itu, seperti diskriminasi rasial, perbudakan, eksploitasi sumber daya, perampasan hak hidup dan lain-lain.
 Ilustrasi agresi militer Belanda/ Foto: Wikimedia Commons Ilustrasi agresi militer Belanda/ Foto: Wikimedia Commons |
Hal ini seperti menyiratkan, bahwa upaya penelitian dalam mengungkap 'borok' sejarah masa silam Belanda, masih berlangsung apa adanya dan belum sepenuhnya. Sampai pada titik ini, permintaan maaf PM Belanda kali ini pun tampak kembali bernilai hampa, sebagaimana permintaan maaf sebelum-sebelumnya yang juga pernah diutarakan oleh Kerajaan Belanda saat berkunjung ke Indonesia atau bahkan walikota Amsterdam.
Meskipun kali ini Rutte mencoba menyampaikan maafnya bersama simpati yang tinggi, rasanya hal ini belum benar dan tidak cukup proporsional. Sebab dosa Belanda di era kolonial seperti kerja rodi, sistem tanam paksa (cultuurstelsel), politik adu domba, dan lain sebagainya akan sulit untuk dilupakan begitu saja apalagi dimaafkan secara cuma-cuma.
Pada salah satu tulisannya mengenai aib masa lalu bangsa, Profesor Ariel Heryanto pernah menyatakan bahwa, "Setiap bangsa menanggung aib kekejaman leluhurnya. Tapi umumnya yang diketahui hanya aib bangsa lain. Bukannya mereka menyangkal atau lupa. Mereka sama sekali tidak tahu-menahu." Beranjak dari pernyataan tersebut, maka pada akhirnya, sikap berani mempelajari dan menerima sejarah sendiri sekalipun pelik, menjadi penting untuk kita lakukan.
 Ilustrasi Cultuurstelsel/ Foto: Wikimedia Commons Ilustrasi Cultuurstelsel/ Foto: Wikimedia Commons |
Terlebih di zaman sekarang, ketika para pemangku jabatan lebih sering membicarakan masa depan dan meninggalkan kebenaran sejarah di pojok gelap jalanan, rasanya, kita sebagai satu kesatuan bangsa yang selalu tampak optimis menyongsong masa depan, perlu kembali menilik bab-bab sejarah yang mulai usang di sudut rak perpustakaan.
Atau, mungkin bisa memulainya dengan mencari tahu sebenarnya: berapa lama kita terjajah Belanda, sehingga klaim tiga setengah abad yang tadinya dipergunakan tokoh-tokoh Bangsa untuk menyulut api perlawanan terhadap kolonial, tidak lagi kita terima secara mentah, apalagi terkunyah sebagai pelajaran di buku-buku sekolah.
Sebab, bukankah Bung Karno, melalui salah satu pidatonya yang monumental namun sulit ditemukan keberadaannya pernah berwasiat, "jangan sekali-kali meninggalkan sejarah"? Jadi, sejarah apa yang ingin kamu dustakan?
(RIA/DIR)