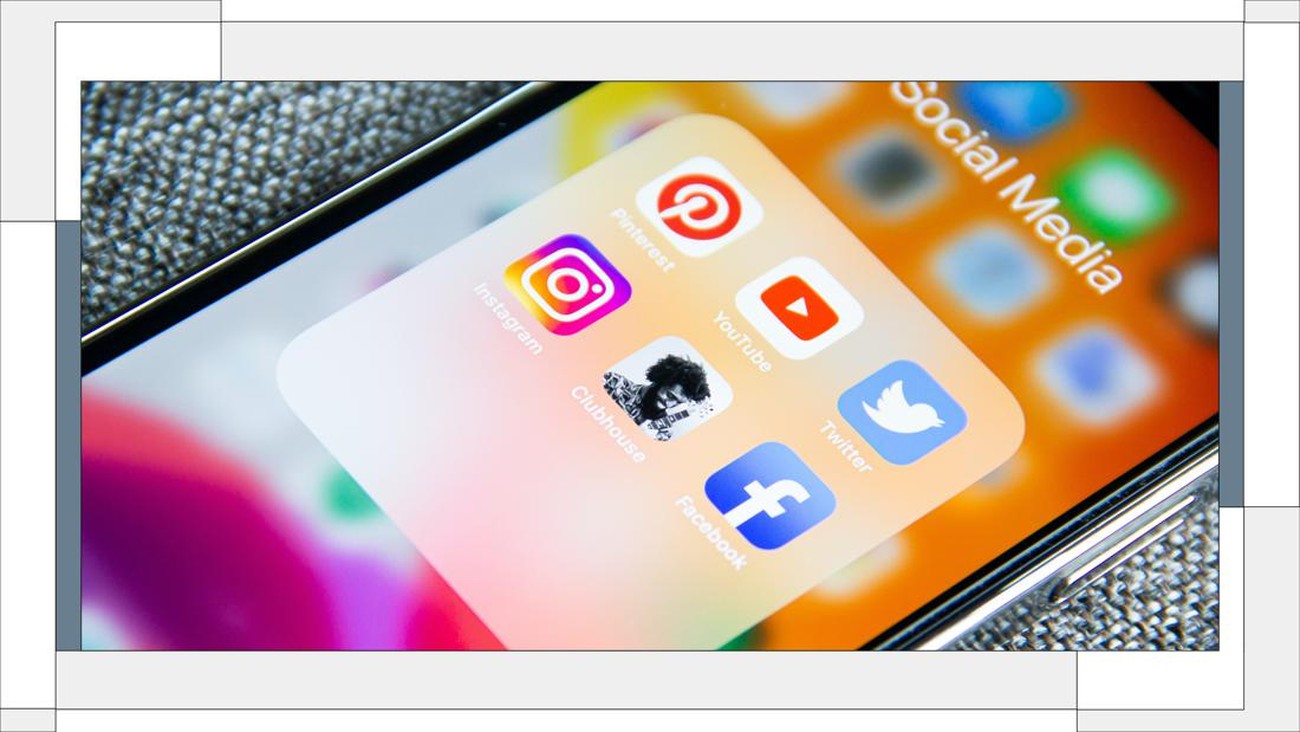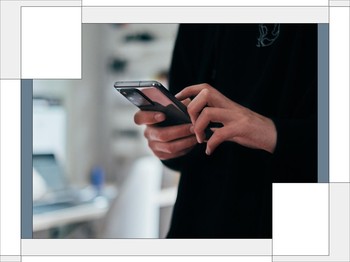Beberapa hari yang lalu, jagat maya dihebohkan dengan sebuah tweet dari akun bernama @dianparamita yang mempermasalahkan penggunaan sendok plastik. Ia mengungkapkan kekesalannya kepada restoran yang tetap memberinya sendok plastik, meski di aplikasi pemesan makanan ia sudah menuliskan catatan "Tanpa Sendok". Hal ini membuatnya marah karena ditakutkan akan menambah sampah plastik dan memperparah kerusakan lingkungan. Tweet tersebut secara detail berbunyi:
"Udah nggak ngerti lagi sama resto2 yang udah dikasih notes "TANPA SENDOK", udah di-DM, bahkan ditelpon, tapi tetep ngasih sendok plastik!!! Kok ignorant bgt sih?! Kurang apa berita tentang sampah plastik merusak alam?? Kok bisa ga peduli?? Plis, bantu saya, saya harus gimana lagi?"
Tidak sampai 24 jam, tweet tersebut langsung mendapat respons yang ramai dari netizen; 2964 retweet, 17500 quote tweet, dan 13200 like. Sebuah ekspresi kemarahan yang berawal dari sendok plastik, berujung menjadi percakapan viral yang mendominasi linimasa. Meski niat dari tweet tersebut baik, tak sedikit yang mengkritiknya.
Tak bisa dipungkiri, banyak orang menggunakan media sosial untuk kegiatan aktivisme. Tweet di atas, misalnya, mengandung pesan-pesan mengenai masalah sampah plastik dan perlindungan lingkungan. Namun, banyak yang menganggap masalah sendok plastik tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan sederhana, tanpa berkoar-koar di media sosial. Contohnya, dengan menyimpan sendok plastik yang sudah diberikan agar bisa dipakai di kemudian hari dan tidak menjadi sampah. Banyak yang akhirnya mempertanyakan mengapa sesuatu yang "sederhana" seperti ini harus di-post dan dibesar-besarkan di media sosial.
 Ilustrasi media sosial/ Foto: Maddi Bazzocco via Unsplash Ilustrasi media sosial/ Foto: Maddi Bazzocco via Unsplash |
Mengejar Clout
Ketika kasus seperti ini terjadi, muncul kecurigaan bahwa post tersebut bertujuan untuk meningkatkan clout. Clout sendiri memiliki arti kekuasaan atau pengaruh. Di era media sosial, istilah clout mengacu kepada pengaruh atau influence yang dimiliki seorang pengguna. Di dunia nyata, status sosial, jumlah kekayaan, dan seberapa luas jejaring pertemanan kerap dijadikan tolok ukur sebesar apa pengaruh yang dimiliki seseorang. Meski demikian, pengaruh seseorang tidak bisa benar-benar diukur melalui angka. Internet dan media sosial telah mengubah hal ini.
Di media sosial, pengaruh seseorang bisa dikuantifikasi dan diukur, sebab pengaruh seringkali disamakan dengan popularitas. Oleh karenanya, pengaruh seseorang bisa diukur melalui jumlah likes, jumlah retweets, dan jumlah followers. Inilah yang disebut sebagai attention economy seseorang bisa mengakumulasi kekayaan dengan mencari perhatian di media sosial. Semakin populer seseorang, semakin besar clout-nya.
Popularitas seseorang di dunia maya bisa dikonversi menjadi kekayaan di dunia nyata. Hari ini, menjadi content creator atau influencers memiliki prospek yang menggiurkan dari segi ekonomi. Tengok saja food vlogger Nex Carlos atau beauty influencer Cindercella. Mereka bisa meraih kesuksesan ekonomi karena orang-orang menyukai konten-konten yang mereka buat di media sosial. Tak hanya itu, mendapatkan perhatian di media sosial bisa membuatmu terkenal dalam waktu yang terhitung singkat. Oleh karena dua hal ini, keuntungan yang menjanjikan dan waktu yang cepat, banyak orang akhirnya melakukan berbagai cara untuk mengejar clout.
Mengejar clout dilakukan secara sederhana. Wujudnya bisa dari yang sederhana seperti memposting foto saat sedang liburan, memposting komentarmu terhadap peristiwa tertentu, hingga membuat konten sensasional seperti prank. Pada dasarnya, apa pun yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan perhatian sebanyak-banyaknya dari pengguna lain. Memang tidak semua post di media sosial bertujuan untuk mencari clout. Sayangnya, karena banyak konten yang sengaja dibuat untuk mengejar clout, hampir semua yang bersirkulasi di media sosial tidak bisa dipisahkan dari motivasi mencari perhatian, bahkan aktivisme sekalipun.
 Ilustrasi influencer/ Foto: Mateus Campos Felipe via Unsplash Ilustrasi influencer/ Foto: Mateus Campos Felipe via Unsplash |
Cloutivism
Di media sosial, aktivisme tumbuh subur. Orang-orang bisa dengan mudah membagikan perspektif mereka soal berbagai isu, mulai dari keadilan sosial hingga perubahan iklim. Tak hanya itu, berbagai NGO juga menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan kampanye mereka. Permasalahannya, tak sedikit juga individu yang memanfaatkan ladang aktivisme untuk memperoleh clout di media sosial, atau biasa disebut cloutivism. Cloutivism adalah aktivisme yang bersifat performatif, sebab tujuannya sekedar untuk mencari perhatian atau mendongkrak popularitas.
Ketika seseorang melakukan cloutivism, muncul pertanyaan apakah ia benar-benar peduli dengan isu yang sedang ia advokasikan. Media sosial telah mengaburkan mana konten yang tulus datang dari maksud baik, mana konten yang sengaja dibuat untuk mencari perhatian. Hal ini bisa berbahaya, karena dengan informasi yang mengalir deras di media sosial, cloutivism bisa membuat kita melupakan isu yang sesungguhnya. Dalam kasus Dian Paramita, misalnya, netizen akhirnya menghabiskan berjam-jam untuk memperdebatkan sendok plastik. Tak hanya itu, banyak juga yang mencaci maki dirinya karena tidak setuju dengan perspektifnya.
Di media sosial, aktivisme yang tujuannya baik bisa berubah menjadi sangat transaksional dan digunakan untuk memoles citra semata. Mereka yang bermaksud menjadi agen perubahan bisa dengan mudah tergelincir menjadi pengejar clout, dan juga sebaliknya.
Meski pelik, jangan sampai cloutivism menghalangi pemanfaatan media sosial untuk aktivisme. Sebab bagaimanapun juga, aktivisme di media sosial bisa melengkapi aktivisme di dunia nyata. Agar tidak terjebak menjadi pengejar clout, ada baiknya sebelum melakukan aktivisme kita mempertimbangkan dulu apa pesan yang ingin disampaikan dan apa tujuan yang ingin diraih. Apakah itu tujuannya untuk mempengaruhi pola pikir, menyebarluaskan pesan, atau mengadvokasi gaya hidup tertentu? Apabila tujuannya untuk sekadar marah-marah dan membuat keramaian, lebih baik pikir ulang dulu sebelum mempostingnya.