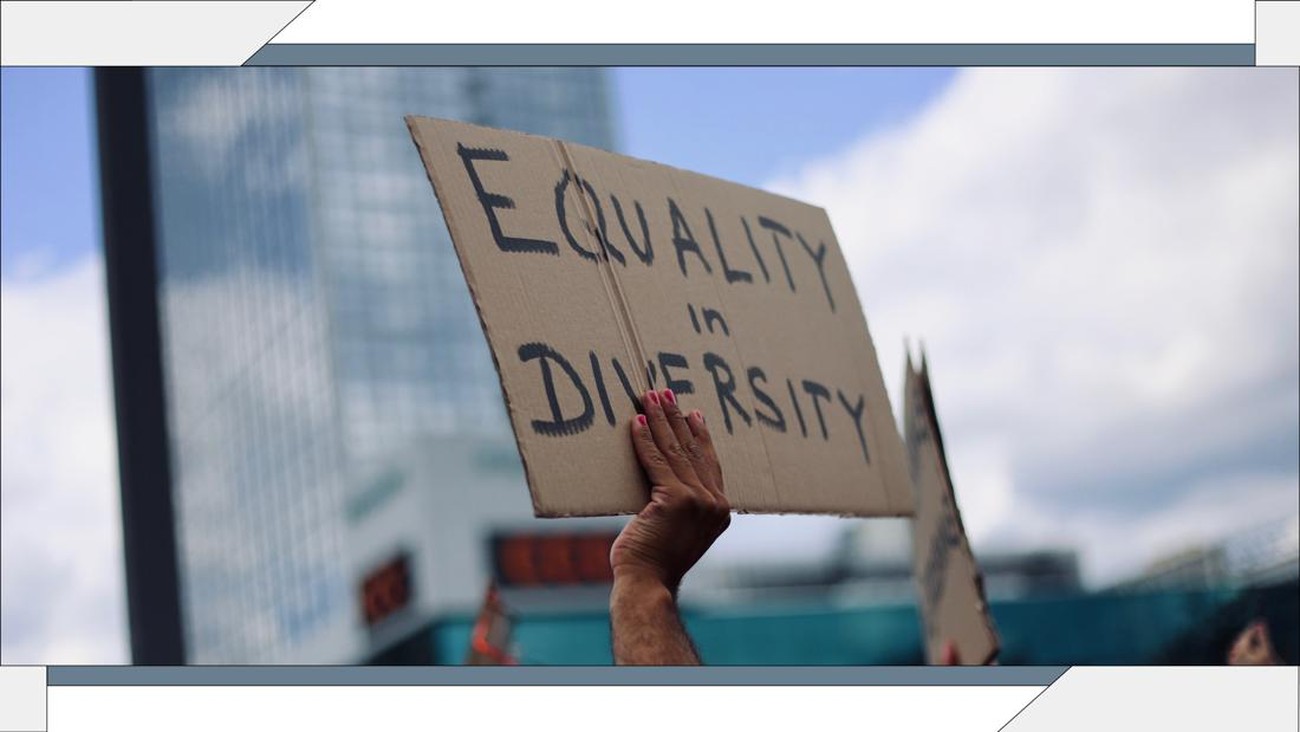Ketika saya beranjak remaja, saya sangat senang ketika melihat karakter Cho Chang muncul di film Harry Potter. Saat beranjak dewasa, saya baru menyadari bahwa rasa senang tersebut muncul karena saya bisa mengidentifikasi sosok di layar kaca dengan identitas saya sendiri, yaitu seorang remaja perempuan Asia.
Namun rasa puas dan bahagia ini tak berlanjut lama, sebab karakter Cho Chang hanya muncul sebentar di film-film Harry Potter. Sepanjang serial film, karakter Cho Chang juga tidak memiliki peran-peran yang begitu berarti dari menjadi love interest Cedric Diggory, hingga menjadi love interest Harry sendiri. Barulah saya sadar, ketidakpuasan ini muncul karena representasi yang bermasalah.
Hingga hari ini, representasi masih menjadi isu yang ramai diperbincangkan, terutama dalam media dan budaya pop. Misalnya, film The Last Airbender dikritik karena melakukan whitewashing dengan menggunakan aktor dan aktris kulit putih untuk memerankan Aang, Katara dan Sokka. Padahal dalam versi animasinya, karakter Aang terinspirasi dari biksu Tibet, sedangkan Katara dan Sokka terinspirasi dari suku Inuit. Orang-orang pun bertanya, mengapa mereka memilih aktor kulit putih untuk memerankannya? Bukankah Hollywood tak kekurangan aktor-aktris Asia yang juga sama berbakatnya?
 Pemeran Aang di film The Last Airbender/ Foto: DenOfGeek Pemeran Aang di film The Last Airbender/ Foto: DenOfGeek |
Permasalahan representasi tidak berhenti di whitewashing saja. Sebenarnya, sudah ada banyak karakter ras minoritas dalam film dan serial yang kita tonton sehari-hari. Namun, banyak dari mereka yang ditampilkan secara stereotipikal, dan seringkali hanya sebagai pelengkap dari pemeran utama kulit putih. Selain Harry Potter, Glee juga sempat dikritik penggambarannya akan karakter minoritas.
Misalnya, selama beberapa season, sosok Mercedes Jones menjadi satu-satunya karakter dari ras Afrika-Amerika di acara tersebut. Dalam Glee, ia digambarkan memiliki kepribadian yang sassy dan lantang, dan juga memiliki bakat menyanyi yang sangat apik. Tapi kehadirannya hanya menjadi tokoh pendukung dari karakter utama Rachel Berry dan Finn Hudson, yang berkulit putih.
 Amber Riley as Mercedes / Foto: Glee Fandom Amber Riley as Mercedes / Foto: Glee Fandom |
Apa yang terjadi di atas disebut sebagai tokenism. Apa itu tokenism? Tokenism adalah ketika sesuatu, seseorang, atau sekelompok orang, ditampilkan sebagai simbol yang mewakili keberagaman. Dalam konteks film, kehadiran karakter token biasanya bertujuan untuk memunculkan narasi keberagaman dalam layar kaca. Tokenism marak terjadi ketika representasi dihadirkan dalam rangka memenuhi keinginan pasar. Sehingga, ia adalah keberagaman yang bersifat performatif dan tidak benar-benar mewujudkan keberagaman.
Dilansir ATTN, Frances Gateward, asisten profesor kajian dan kritik media di Cal State Northridge mengatakan, bahwa bagi orang kulit putih mungkin tidak akan menyadari permasalahan ini karena peran yang tersedia untuk mereka sangat banyak dan beragam. Sedangkan bagi kelompok minoritas, kehadiran mereka hanya sebatas simbol atau token dari keberagaman, tetapi karakter mereka tak diberi cerita yang berarti. Praktik seperti ini melukai kelompok minoritas.
Mereka jarang sekali direpresentasikan, namun ketika muncul karakter yang mewakili kelompok mereka, karakter tersebut hanya ditampilkan melalui stereotip yang berujung pada misrepresentasi. Misalnya, aktris yang memerankan Cho Chang, Rachel Rostad, sempat mengkritik bagaimana karakternya di Harry Potter merupakan representasi yang salah akan perempuan Asia.
Ia digambarkan tidak memiliki kedalaman emosional dan hanya memiliki satu dimensi; lemah lembut dan nyaris tak pernah bersuara. Tak hanya itu, penggunaan nama Cho Chang juga keliru, sebab keduanya merupakan nama belakang yang lazim digunakan oleh orang Korea. Padahal, karakter Cho adalah keturunan Tionghoa.
 Ilustrasi tokenism/ Foto: Monstera/Pexels Ilustrasi tokenism/ Foto: Monstera/Pexels |
Tokenism juga berpotensi membangun sebuah ilusi bahwa masalah representasi telah terpecahkan dan inklusivitas telah berhasil diwujudkan. Sementara itu, masalah sebenarnya akan tetap berlanjut tanpa adanya solusi konkret. Dengan kata lain, ia adalah solusi instan yang bisa membuat orang-orang lupa akan masalah yang sedang terjadi. Produser film, sutradara, dan penulis pun bisa membebaskan diri dari tanggung jawab untuk melakukan riset yang mendalam dan merepresentasikan sebuah budaya secara akurat.
Merespon kritik publik, banyak produser film akhirnya mencoba menghadirkan representasi yang lebih beragam dalam karya-karya mereka. Netflix, misalnya, telah menjadikan keberagaman sebagai prioritas dalam film dan serial yang mereka buat. Salah satunya bisa kita lihat dalam serial Never Have I Ever yang menampilkan karakter utama Devi Vishwakumar, seorang remaja keturunan India yang besar di Amerika.
Dalam Never Have I Ever, karakter Devi menavigasi berbagai tantangan kehidupan. Mulai dari masalah kesehatan mental, hidup percintaan, hingga menegosiasikan identitasnya yang terbelah antara dua budaya. Di sini, identitas Devi tidak semata-mata didefinisikan melalui karakternya sebagai keturunan India. Ras hanya menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi keseluruhan konflik cerita. Penonton pun diajak untuk melihat Devi dari berbagai sisi.
 Never Have I Ever TV Series/ Foto: Detik.com Never Have I Ever TV Series/ Foto: Detik.com |
Perlu diingat, tokenism tak hanya terjadi di industri perfilman. Ia terjadi hampir di setiap aktivitas kita sehari-hari, misalnya dalam dunia politik. Contohnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mengharuskan partai politik untuk menyediakan kuota keterwakilan sebesar 30 persen bagi perempuan.
Di satu sisi, kebijakan ini bisa menjadi landasan hukum untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Namun di sisi lain, partisipasi dalam politik tidak bisa hanya diukur melalui angka. Hingga sekarang saja, saya belum mendapati politikus-politikus perempuan yang suaranya benar-benar bisa mewakili kepentingan perempuan. Sama seperti tokenism di film, ketika keterwakilan hanya menjadi kewajiban, ia justru bisa mengalihkan kita dari tujuan sebenarnya.
Representasi penting sebab ia memberikan ruang untuk kelompok-kelompok minoritas yang biasanya terpinggirkan, untuk memiliki suara. Keberagaman tak seharusnya hanya menjadi checkbox yang harus diisi-sebuah syarat atau formalitas yang harus dipenuhi demi menerima feedback positif dari penonton. Ketika keberagaman diperlakukan bak kewajiban, maka tujuan utamanya, yaitu untuk membangun ruang yang inklusif akan semua orang, tidak akan bisa terwujud. Representasi harus selalu diusahakan dan keberagaman harus selalu diwujudkan, tapi tokenism bukanlah solusinya.
(ANL/DIR)