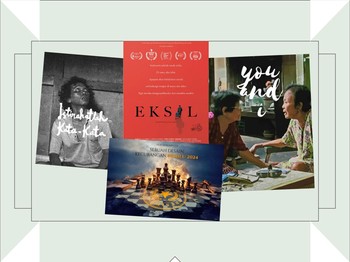Terdapat satu lagu yang terus terngiang dalam benak ketika menyaksikan Eksil—"Trauma, Irama" oleh Majelis Lidah Berduri yang merupakan track kedelapan mereka dari album NKKBS Bagian Pertama. "Kenang kukenangi malam kukenang/Malam di tanah lahirku kukenang/Rindu kurindu ibuku kurindu/Jauh di seberang lautan kurindu", begitu kira-kira lirik pembuka yang seakan menggambarkan kisah mereka yang tertuang pada layar.
Eksil (judul internasional: The Exiles) karya Lola Amaria mengangkat tentang kisah para eksil yang dicampakkan oleh tanah air; mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang dikirim untuk menuntut ilmu di negeri asing, namun kemudian tak bisa pulang karena pergolakan tahun 1965. Afiliasi dengan PKI, hubungan keluarga, hingga kecurigaan-kecurigaan tak berdasar menghalangi jalan para pelajar muda ini ke rumah. Mereka yang merantau menuntut ilmu demi negara, akhirnya malah diasingkan oleh negara—tersebar ke berbagai penjuru dunia tanpa kepastian.
Kerinduan di Pengasingan
Adalah Asahan Aidit, Chalik Hamid, Djumaini Kartaprawira, Kuslan Budiman, Sardjio Mintardjo, Sarmadji, Hartoni Ubes, I Gede Arka, Tom Iljas, dan Waruno Mahdi nama-nama dari para eksil ini. Mereka yang menolak membuang kepercayaan pada Soekarno dan tunduk pada rezim Orde Baru. Tentu sikap ini juga dilengkapi dengan kesiapan bahwa nasib mereka di perantauan akan tak menentu, namun tidak ada satu pun dari mereka yang menyangka bahwa mereka akan "terdampar" selama itu.
Walau peristiwa yang melatarbelakangi kisah-kisah dalam film ini sangat besar dan kompleks—dengan aktor-aktor internasional, perang ideologis, dan perebutan kekuasaan—namun fokus Eksil justru "kecil". Kehidupan-kehidupan yang terpengaruh, bagaimana peristiwa ini membentuk diri mereka, hingga implikasi pengasingan ini bagi keluarga yang ditinggalkan membentuk porsi utama Eksil.
Pengalaman ditelantarkan oleh negara sendiri tentu memberikan luka-luka yang tak selalu tampak. Ada dari mereka yang merelakan istrinya dinikahi oleh temannya sendiri di kampung halaman, ada yang kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain karena trauma, ada pula yang ditolak untuk bertemu oleh keluarga di kampung halaman ketika akhirnya berhasil pulang.
Krisis identitas pun tak luput dialami oleh mereka. Jika tetap menjalani kehidupan sebagai individu stateless, mereka tak akan pernah bisa kembali menginjakkan kaki di tanah kelahiran, namun menjadi warga negara asing—termasuk di antaranya adalah penjajah kita di masa silam—juga adalah keputusan yang tak mudah untuk diraih. Menjadi warga negara asing pun berarti menerima kenyataan bahwa Indonesia tidak akan kembali menerima mereka, bahkan setelah kepemimpinan negara silih berganti. Ini pun adalah bentuk kompromi dengan kehidupan, yang semata-mata dilakukan justru berdasarkan kerinduan pada Indonesia.
Pada satu momen, terlontar pertanyaan, jika seorang pembunuh saja memiliki kepastian soal masa hukumannya, mengapa para eksil yang tidak bersalah ini harus terombang-ambing tanpa kepastian selama puluhan tahun? Mereka pun menceritakan sendiri bahwa kecintaan mereka kepada Indonesia adalah sesuatu yang irasional—untuk apa mencintai negara yang mengenyahkan mereka?
Namun, koneksi terhadap tanah air memang lebih kuat dibanding logika. Keseluruh eksil ini tetap mengelilingi diri dan kehidupan mereka dengan serpihan-serpihan kecil Indonesia—pohon pisang, rempah-rempah, hingga buku-buku Indonesia. Berita mengenai tanah air pun menjadi santapan rutin yang tidak pernah dilewatkan. Masing-masing tetap teguh memperjuangkan "Indonesia" dalam caranya tersendiri, baik menulis, mengkritisi pemerintahan, hingga mengarsipkan material-material tentang Indonesia yang akan termakan waktu tanpa upaya-upaya seperti ini. Walaupun mereka sudah tidak lagi diterima dengan lapang dada, hati mereka tetap terbuka lebar untuk tanah air.
Rezim Orde Baru yang sudah runtuh pun bukan berarti benar-benar berakhir. Ia menjelma menjadi hantu yang bersembunyi dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti hantu, ia juga menjelma ke dalam bentuk-bentuk lain seperti radikalisme gaya baru. Bahkan setelah puluhan tahun, Indonesia masih takut terhadap satu ideologi—pemikiran yang bahkan tak sepenuhnya dipahami oleh kebanyakan masyarakat Indonesia.
Saya bukan termasuk dari generasi yang diwajibkan menonton Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI, namun propaganda anti komunisme masih mengakar kuat pada kurikulum masa saya bersekolah. Kita selalu diajarkan untuk membenci dan mewaspadai "pemikiran kiri", tanpa mengetahui fakta peristiwa G30S, apa lagi nasib saudara-saudara kita yang ditelantarkan negara. Mereka yang kecintaannya pada Indonesia mungkin jauh lebih besar dari kita, namun dicampakkan dan dilupakan. Tentu berbagai kisah yang terkandung di film ini pun hanya sebagian kecil dari ratusan eksil Indonesia. Berapa banyak dari kisah mereka yang tak pernah kita dengar? Yang berusaha dilupakan oleh negara? Yang menemui akhir hayat tanpa rekonsiliasi?
Dengan mayoritas film berbentuk wawancara langsung dengan para sumber, Eksil menghadirkan narasi yang mengalir dan humanis. Kita sebagai penonton dibawa menyaksikan kehidupan mereka di "rumah baru", dan bagaimana ke-Indonesia-an mereka termanifestasi dalam keseharian. Teknis pengambilan gambar yang kadang shaky menambah kesan grounded dari film yang bernas ini. Walau getir, tak sedikit momen yang mengundang senyum dalam Eksil—bukti tentang kekuatan manusia untuk terus bertahan di hadapan kehidupan yang tak selamanya indah.
Jika sejarah ditulis oleh pemenang, Eksil justru memberi suara bagi mereka yang dibungkam bahkan tanpa diberi kesempatan untuk melawan. Walau bagian chorus dari "Trauma, Irama" berbunyi "Trauma irama, denyut nadiku kembara/Trauma irama, terusir 'ku selamanya", hal ini tentu tidak berlaku secara harfiah bagi para eksil di film ini, namun nyatanya Indonesia yang mereka kenal telah hilang selamanya. Sekarang, yang ada hanya sisa-sisa familiaritas dengan hantu-hantu yang menunggu di pojokan.
(alm/tim)